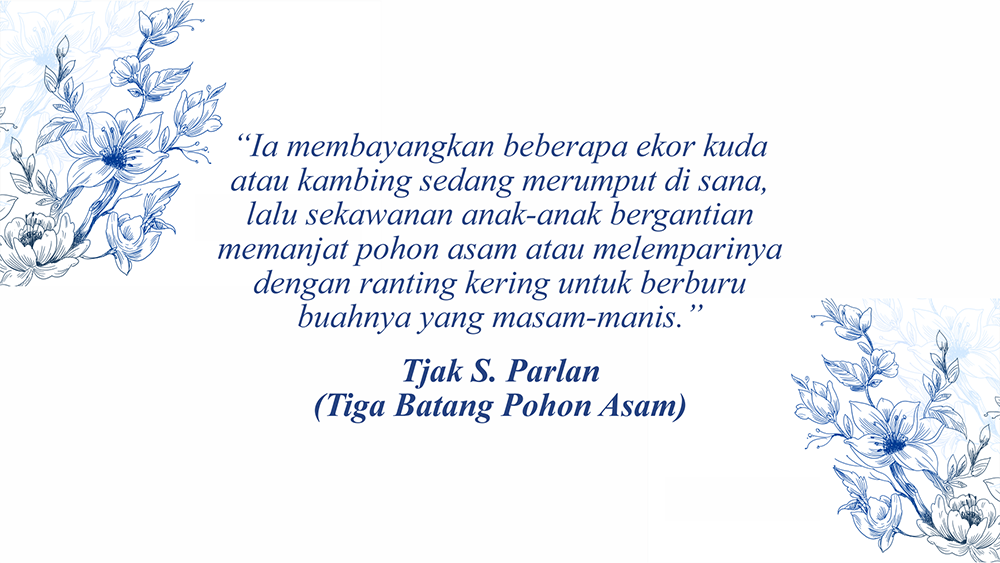
Tiga Batang Pohon Asam
Bertahun-tahun setelah pohon asam itu ditebang, Abu Bakar kerap menyesal. Ia pikir setelah menebang pohon asam itu, amarahnya akan terobati. Ternyata tidak. Justru ia merasa semakin kehilangan. Dia kehilangan kaki sebelah milik anaknya dan redupnya harapan yang menyertainya; dia juga kehilangan pohon asam itu—pohon asam yang kerap dijadikan tempat berlindung orang-orang dari hujan atau terik matahari yang menyengat.
“Sejak dulu tempat ini seperti lahan mati,” ujar Abu Bakar. “Coba kau pikir, siapa juga yang mau menanam sesuatu di lahan seperti ini?”
Seraya mendengarkan cerita Abu Bakar, Ahmadi mengedarkan pandangannya ke lahan yang membentang. Di atas kontur tanah yang keras dan bergelombang itu, aneka tumbuhan lahan tandus bersikeras hidup; mereka bertahan dalam kemarau yang menyengat sampai tiba musim penghujan yang menurunkan mukjizat.
“Aku lihat di sana masih ada pohon asam,” ujar Ahmadi, tangannya menunjuk ke kejauhan.
Matahari begitu terik. Cahayanya seolah tumpah begitu saja di atas topi pandan lebar yang mereka kenakan. Cahaya itu kemudian menyebar ke seluruh ladang—lahan berbatu yang membentang hingga ke bukit-bukit berwarna biru agar-agar di kejauhan. Abu Bakar mengintip dari balik telapak tangannya yang kasar-legam. Keningnya berkerut-kerut dan matanya menyipit.
“Itu salah satu yang bisa tumbuh dan bertahan. Tak tahu siapa yang menanamnya.”
“Tapi kelihatannya tak begitu subur. Maksudku, itu bukan jenis pohon asam yang rindang. Atau mungkin karena umurnya sudah terlalu tua, ya?”
Kening Abu Bakar kembali berkerut-kerut. Lalu, seperti sedang menaksir-naksir sesuatu dan menemukannya, ia mulai manggut-manggut.
“Sepertinya, itu sejak kakek-bayutmu mulai mencoba menanam sesuatu. Aku juga tak tahu, kenapa pohon yang itu seperti sekarat sepanjang tahun. Hidup segan, mati tak mau.”
“Tapi setidaknya belum ditebang.”
Abu Bakar terbatuk-batuk kecil. Ia menyeret langkahnya melewati jalan setapak. Baru beberapa langkah, langsung terhenti. Matanya tertuju pada puntung rokok yang tercecer di antara semak-semak rendah yang kering. Mungkin sejumlah penambang liar yang baru saja turun dari bukit pernah mengaso dan merokok di tempat itu. Beberapa hari lalu, seorang penggembala kambing menemukan sebuah titik api di dekat sumber mata air lama tidak jauh dari pohon asam tua itu. Untung saja angin sedang tenang sehingga titik api itu lebih mudah dipadamkan.
“Aku harap, tak ada lagi yang akan menebang apa pun,” ujar Abu Bakar seraya memastikan puntung-puntung rokok itu telah benar-benar ringsek di bawah telapak sepatu bot-nya.
“Kudengar ada kebakaran kecil minggu lalu,” timpal Ahmadi.
Abu Bakar melepaskan napasnya, lalu memandang jauh ke atas bebukitan. Beberapa hari belakangan mendung tampak menggelayut di atas bebukitan itu, terutama ketika sore hari. Nyatanya, hujan belum juga turun barang sejenak. Berita-berita tentang cuaca masih memberikan harapan: tidak akan ada kemarau panjang tahun ini. Namun, Tuhan terkadang memberikan takdir yang berbeda dibanding ramalan cuaca—dan itulah yang terjadi di tempat ini.
“Tahun lalu malah banjir besar di hulu,” ujar Abu Bakar. “Kadang-kadang repot. Saat kemarau panjang, ada saja lahan yang terbakar. Tapi sewaktu hujan, malah banjir.”
“Sepertinya, dulu-dulu tidak seperti itu, ya?”
“Tak pernah. Tak pernah ada banjir bandang,” tegas Abu Bakar.
Menurut Abu Bakar, dulunya bukit-bukit itu juga cukup lebat dan hijau. Meskipun di sejumlah tempat tanahnya berbatu, tapi aneka tumbuhan khas lahan kering masih bisa bertahan. Orang-orang kampung—bahkan dari kampung terjauh—yang gemar berburu, kerap melintas di jalan setapak itu sambil memikul hewan buruan tangkapannya; terkadang seekor babi hutan yang gemuk, tidak jarang seekor rusa jantan dewasa, atau sesekali mereka cukup senang dengan seekor ayam hutan. Para pencari kayu bakar masih cukup mudah memilih kayu dan menebangnya untuk kebutuhan sehari-hari di rumah mereka.
Namun, pada suatu hari di musim paceklik, sekelompok pemburu buah gadung telah menggali tanah terlalu dalam. Di ambang keputusasaannya, salah seorang di antara mereka menemukan sejenis batuan yang ditengarai mengandung emas—dan itu benar adanya. Berita pun menyebar dari mulut ke mulut. Dan sejak saat itu, tanah di bukit itu terus digali, bahkan oleh orang-orang dari luar pulau yang telanjur tergiur dengan kisah-kisah gemilang perburuan batu mulia.
“Apa boleh buat,” jelas Abu Bakar. “Bahkan sebuah tambang legal dan besar, katanya akan segera beroperasi. Kau tahu informasi soal itu, kan?”
“Itu benar adanya. Beritanya sudah tersebar di mana-mana,” tanggap Ahmadi.
Tiba-tiba Abu Bakar mengarahkan telunjuknya ke suatu tempat, sebuah gugusan bukit yang tampak mulai dipayungi gumpalan awan kelabu. “Di sana,” ujarnya kemudian.
Ahmadi memandang ke arah telunjuk Abu Bakar dan ia mendapati pemandangan yang berbeda. Sejumlah lahan bukaan tampak di sejumlah titik. Warnanya sungguh kontras dengan sekitarnya yang masih tampak biru agar-agar.
“Oh, itu areal yang luas. Sampai berapa tahun bukit-bukit itu akan dilubangi?”
“Setelah habis kontrak,” tanggap Abu Bakar. “Mungkin setelah habis isinya. Kau tahu sendirilah!”
Tentu saja, Ahmadi tidak asing dengan hal semacam itu. Ia kerap mendengar cerita-cerita getir tentang hutan-hutan atau bukit-bukit yang digunduli atau dilubangi. Namun sebaliknya, tidak jarang juga ia mendengar cerita-cerita keberhasilan dari para pemburu emas.
“Kau masih ingat Mursyid?” tanya Abu Bakar.
Ahmadi mengernyitkan dahinya, mencoba mencari-cari nama itu di dalam benaknya. Namun, sepertinya dia nyaris gagal menemukannya. Untung saja Abu Bakar mengingatkannya dengan sebuah peristiwa.
“Bocah yang mengajarimu memanjat pohon asam pada suatu sore. Dan kamu jatuh, lalu dibawa ke tukang urut.”
“Ya, Tuhan! Aku mulai ingat sekarang. Bagaimana kabarnya?”
“Mursyid lumayan kaya sekarang. Kabarnya karena emas.”
Ia sedang menikmati liburan akhir tahun waktu itu. Itu menjelang tahun kedua ia duduk di Sekolah Dasar di kota. Ibunya mengantarnya ke rumah kakeknya dan meninggalkannya selama dua minggu penuh. Cukup banyak anak-anak kampung yang setiap hari bermain-main apa saja bersamanya. Mungkin karena itulah ia tidak bisa mengingat satu demi satu nama mereka setelah rentang waktu yang begitu panjang. Salah satu yang kerap bersamanya adalah Mursyid. Bocah tengil yang kerap mengajaknya memanjat pohon asam dan mencari buahnya yang rasanya masam-manis.
Ketika membayangkan tubuh kecilnya pernah meluncur dari salah satu dahan pohon asam dan terantuk tanah berbatu, giginya terasa ngilu. Namun, kenangan tentang pohon asam itu membuatnya ingin bernostalgia.
“Mana pohon itu sekarang?” ujar Ahmadi seraya mengedarkan pandangannya ke sekitar.
Sejumlah pohon asam memang masih tumbuh di tempat itu. Ada tiga atau empat yang tumbuh berjarak di sejumlah titik. Namun, tampaknya pohon-pohon itu usianya belum cukup tua. Bertahun-tahun setelah ia dan kedua orang tuannya tinggal di kota yang jauh, Abu Bakar telah menanamnya kembali.
“Seorang penggembala yang berteduh di bawah pohon itu, hampir saja jadi korban sambaran petir,” jelas Abu Bakar. “Itu musim hujan yang disertai angin kencang, juga petir yang ganas. Sebagian dari pohon itu hangus terbakar dan lambat laun mati kering dimakan rayap.”
“Oh, aku kira …”
“Sayang sekali, pohon masa kecilmu itu sudah tak ada. Coba masih ada, kamu bisa foto berdua dengannya, ya …” ujar Abu Bakar.
Ahmadi mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya tengah dirasakan oleh Abu Bakar. Hal itu justru mengingatkannya pada sebuah kisah yang pernah diceritakan sekilas oleh ayahnya. Menurut ayahnya, pada suatu masa Abu Bakar pernah sangat murka dan menebangi sejumlah pohon asam. Ayahnya tidak pernah menceritakan alasan yang jelas mengapa Abu Bakar sampai melakukan hal semacam itu.
“Tapi, sekarang aku bisa melihatnya sendiri,” kata Ahmadi dalam hati, ”betapa ia punya ketertarikan yang lebih pada pohon-pohon…”
Abu Bakar menepuk pundak Ahmadi, dan mengajaknya menyeberang ke sisi jalan setapak. Mereka melewati tanah berbatu yang di sela-selanya dihuni oleh tumbuhan semak berwarna pucat. Seekor bengkarung berwarna cokelat keabuan yang melintas di depan mereka, segera bersembunyi di balik sebongkah batu ketika Ahmadi iseng mengentakkan kakinya.
“Kau takut sama ular?” tanya Abu Bakar tiba-tiba.
Ahmadi menggeleng. Namun, tampaknya ia tidak begitu yakin. Ia teringat seorang teman dekatnya pernah mengalungkan ke lehernya mainan ular-ularan dari karet dan itu membuatnya lari tunggang langgang seraya berteriak histeris. Faktanya, ia juga pernah secara tidak sengaja menginjak seekor ular sawah dan itu membuatnya tidak terlalu takut. Ia hanya merasa geli dan itu membuatnya bergidik setiap kali mengingatnya. Kini, ia merasakan hal yang sama ketika Abu Bakar menunjukkan sesuatu kepadanya.
Selongsong kulit ular itu meringkuk di atas sebongkah batu. Abu Bakar mendekat dan menyentuhnya dengan ujung sepatu boots-nya. Ia tampak berhati-hati sekali. Matanya menyelidik ke sekitar seolah-seolah memastikan bahwa tidak ada bahaya yang bisa mengancam dari balik bebatuan atau semak-semak kering di sekitarnya. Selongsong yang kempes itu tampak masih utuh. Ketika Abu Bakar menyibaknya dengan ujung parang, Ahmadi terbayang seekor kobra yang siap memamerkan moncongnya; leher ular itu memipih dan membentuk sebuah tudung berwarna hitam yang mengisyaratkan ancaman. Seketika, Ahmadi pun bergidik.
“Ini jenis yang berbahaya,” ujar Abu Bakar dengan tenang. “Terkadang memang masih muncul di sekitar sini. Dan sepertinya, yang ini belum terlalu lama berganti kulit.”
“Oh, masih sering muncul di sini. Apakah ini sejenis kobra?” tanggap Ahmadi.
“Benar sekali. Ini memang kobra.”
Menurut Abu Bakar, kobra sebenarnya adalah jenis ular pemalu. Binatang melata berbisa ini akan bersembunyi dan melindungi dirinya manakala bertemu dengan sosok lain yang lebih besar darinya. Hanya saja, yang seperti itu tidak pernah berlaku bila situasinya berbeda.
“Tak ada ular yang akan menggigit terlebih dulu, kecuali merasa terganggu atau terpojok,” jelas Abu Bakar.
“Oh, aku selalu teringat ayah kalau melihat ular.”
Abu Bakar berhenti menyentuh selongsong kulit ular itu. Ia menatap wajah Ahmadi beberapa saat seolah-olah sedang mencari-cari sesuatu di sana. Wajah Ahmadi begitu mirip dengan Rasyid, anak laki-laki satu-satunya. Bahkan saking miripnya, ketika Ahmadi tumbuh dewasa, banyak orang yang kerap menyebut mereka saudara kembar yang berbeda tahun kelahiran.
“Ada apa dengan ayahmu?”
“Ayah sangat membenci ular,” jawab Ahmadi. “Benar-benar membencinya!”
Abu Bakar kembali terbatuk-batuk kecil. Langkahnya bergegas meninggalkan selongsong kulit reptil itu di tempatnya semula. Ahmadi mengekor saja di belakang punggungnya. Dalam usia tuanya, Abu Bakar masih memiliki daya tahan fisik yang mengagumkan. Ia adalah sosok yang ramping dan berotot dengan ketajaman mata seorang yang teguh pendirian. Sepanjang hidupnya, ia telah bertungkus lumus dengan kondisi alam sekitarnya yang kerap kurang bersahabat. Sejak remaja, ia telah terbiasa mengurus puluhan ekor kuda yang dimiliki orangtuanya. Kuda-kuda itu dilepas-liarkan lalu digiring ke sebuah areal peternakan yang menempati sebentang lahan yang berkontur lebih rata. Kuda-kuda itu diperah di sana dan menghasilkan susu segar yang disukai banyak orang.
Namun, ia selalu memiliki mimpi yang lain. Setelah kedua orangtuanya meninggal, ia harus melanjutkan sesuatu yang sudah dimulai oleh pendahulunya itu. Ayahnya telah menitipkan sebentang lahan mati yang tidak sempat digarap sepenuhnya semasa masih hidup. Ayahnya telah menanam berbagai jenis pohon. Banyak di antaranya sekarat, lalu tidak bisa bertahan sama sekali. Ada tiga batang pohon asam yang bisa tumbuh dengan rimbun, tapi kini bahkan tidak menyisakan tunggulnya. Abu Bakar telah menghabisinya. Dan ia menyesal, meskipun terus berusaha menumbuhkan biji-biji dan batang-batang yang lain.
“Kita berteduh di sini,” ujar Abu Bakar.
Mereka duduk di bawah naungan pohon asam yang lain. Abu Bakar membuka topi lebarnya dan mendongak dan matanya mulai memeriksa rimbunan daun asam. Dari celah-celah rimbunan daun asam itu, satu-dua cercah matahari jatuh menimpa wajahnya yang berkeringat. Pohon asam itu terhitung masih muda. Abu Bakar telah menanamnya beberapa tahun silam.
“Kau tahu, kenapa ayahmu sangat membenci ular?” tanya Abu Bakar.
Ahmadi menggeleng. Seingatnya, ayahnya memang tidak pernah menceritakan apapun yang menyebabkannya membenci ular sedemikian rupa.
“Aku justru heran,” jawab Ahmadi. “Kalau pun harus membenci sesuatu, kupikir selama ini ayah akan membenci kendaraan. Ya, sesuatu yang membuatnya mengalami kecelakaan.”
Kening Abu Bakar berkerut-kerut dan matanya menyipit. Ia tampak heran dengan jawaban Ahmadi. Lalu dia membayangkan sebuah peristiwa kecelakaan—sesuatu yang belum pernah terjadi dalam hidupnya, juga dalam hidup anak laki-laki satu-satunya.
“Jadi, ayahmu pernah kecelakaan?”
“Perisitiwa itu terjadi sebelum aku lahir,” jawab Ahmadi sedikit heran. “Bagaimana mungkin kakek lupa? Kakek pasti sedang bercanda.”
Abu Bakar berusaha tersenyum. Untuk beberapa saat ia serahkan pikirannya ke seluruh bentang lahan yang bisa dijangkau dengan pandangan matanya. Ia membayangkan beberapa ekor kuda sedang merumput di sana. Lantas sekawanan anak-anak bergantian memanjat pohon asam atau melemparinya dengan ranting kering untuk berburu buahnya yang masam-manis. Bayangan-bayangan itu pun berhenti sejenak, terantuk pada seekor kobra berwaran hitam legam yang mengancam dari balik semak-semak di bawah pohon asam.
“Penyebab utama ayahmu harus duduk di kursi roda, bukan karena kecelakaan lalu lintas,” jelas Abu Bakar. “Kalau mau, kau boleh mendengar cerita yang sesungguhnya. Lagi pula, cepat atau lambat kau juga akan mengetahuinya. Kau mau mendengarnya dariku?”
Ahmadi menatap wajah Abu Bakar, lalu mengangguk kecil. Ia percaya kakeknya tidak akan pernah membohonginya.
***
“Sekarang, coba kau lihat!” ujar Abu Bakar seraya mengarahkan telunjuknya ke suatu tempat. “Menurutmu, sedang apa orang-orang itu?”
Rasyid memandang ke sebuah mata air tidak begitu jauh dari tempat mereka duduk. Tiga orang terlihat sedang membasuh muka. Lalu seseorang di antaranya merendam kepalanya beberapa saat. Mereka sepertinya sedang lelah dan kehausan. Seseorang yang baru muncul dari jalan setapak berbatu, langsung bergabung dengan kelompok kecil itu. Orang yang baru datang itu menenteng jeriken kecil yang segera dipenuhinya dengan air.
“Orang-orang itu sedang membasuh muka. Ada juga yang mengambil air,” jawab Rasyid.
“Menurutmu untuk apa seseorang di sana mengambil air?”
“Mereka akan meminumnya.”
“Kau yakin?”
Rasyid mengangguk tanpa ragu. “Aku pernah mengambil air di tempat itu dan meminumnya langsung dengan tanganku,” ujarnya kemudian.
Abu Bakar tersenyum. Ia menatap wajah remaja tiga belas tahunan itu untuk beberapa saat. Ketika pandangannya beralih ke sumber mata air, seseorang tampak sedang berwudu. Di tempat yang terkadang tidak luput kekeringan itu, sumber mata air adalah sebuah mukjizat. Air di tempat itu masih jernih dan segar. Jika musim hujan tiba, air akan mengalir cukup lancar melewati kali kecil yang berkelok hingga ke ladang-landang tadah hujan milik warga desa. Para peladang, penggembala, perambah hutan, pencari kayu atau siapa saja yang melintas di jalan setapak itu, dipastikan akan singgah ke sumber mata air. Mereka akan memenuhi jerikennya dengan air dari sumber mata air yang sejuk itu; atau hanya sekadar ingin membasuh muka, merendam kepalanya yang terlalu lama terpapar terik matahari; satu atau dua orang mungkin juga akan berwudu dan menunaikan ibadahnya sebelum waktunya terlambat.
“Sekarang, apa kau tahu kenapa aku mengajakmu memperhatikan mereka?” tanya Abu Bakar.
Rasyid menggeleng. Ia tampak heran dengan pertanyaan ayahnya. Sumber mata air itu bukan tempat yang asing bagi mereka. Rasyid sendiri, jika musim hujan tiba, juga sering pergi ke mata air itu bersama teman-temanya. Ketika musim hujan debit air akan lebih tinggi dan sejumlah anak desa akan turun mandi.
“Kau ingat kejadian tiga hari lalu? Aku menegurmu waktu itu.”
Tiga hari sebelumnya, Rasyid berdiri di tepian ceruk sumber mata air itu. Ia membuka ritsleting celananya seraya bersiul-siul. Air kencingnya mengucur deras dan menimbulkan riak-riak kecil di permukaan air. Abu Bakar mengelus dadanya ketika mendapati anak laki-lakinya melakukan hal semacam itu. Ia pun menegurnya agar Rasyid tidak lagi melakukan hal yang sama.
“Aku tahu sekarang,” jawab Rasyid kemudian.
“Syukurlah, kalau sudah tahu,” tanggap Abu Bakar seraya memberikan sebuah tepukan kecil ke pundak Rasyid. “Sewaktu kau berdiri di sana dan membuang air kencingmu, kau tidak akan pernah tahu siapa selanjutnya yang akan datang dan akan melakukan apa. Bisa saja ayahmu yang sedang kehausan. Atau ibumu, atau orang lain yang mungkin akan berwudu, atau mandi, atau hanya membasuh muka. Dan air yang jernih dan segar itu baru saja tercemar oleh air kencingmu. Bisa kau bayangkan itu, kan?”
Rasyid hanya menunduk. Matanya menekuni seekor belalang berwarna khaki tua yang sedang tersuruk-suruk di atas permukaan tanah yang bergelombang. Beberapa saat kemudian belalang itu terbang rendah dan hinggap di antara rumput belulang. Itu suatu siang yang cukup terik menjelang datangnya musim penghujan yang didambakan oleh semua orang. Abu Bakar berpikir untuk mulai menanam sesuatu di lahan warisan orangtuanya. Ayahnya telah menumbuhkan sejumlah pohon di lahan yang nyaris mati itu. Tiga batang pohon asam tumbuh di sejumlah tempat. Yang paling rindang tumbuh di dekat jalan setapak, berbatasan dengan lahan berbatu milik orang lain yang sudah lama tidak terurus. Orang-orang yang melintas di tempat itu, biasanya akan singgah untuk berteduh, sekadar menunggu keringat mengering—jeda sebentar sebelum melanjutkan perjalanannya kembali.
“Tampaknya, kau harus mulai membantuku menanam sesuatu,” ujar Abu Bakar seraya bangkit dan meninggalkan tempat itu.
Rasyid memandang sekali lagi ke sumber mata air itu. Tampak sepi. Orang-orang itu—yang mungkin para penggali buah gadung—sudah berlalu dari sana. Mereka berjalan berurutan dalam sebuah kelompok kecil. Dua orang di antaranya memanggul goni. Rasyid membayangkan seonggok beban yang memberati punggung mereka.
“Kau masih lebih beruntung, Rasyid,” ujar Abu Bakar. “Lihatlah mereka, memanggul buah gadung untuk keluarganya. Sepanjang hari mereka keluar masuk hutan. Di tengah terik seperti ini…”
“Mereka pasti kehausan dan lapar,” ujar Rasyid seraya mengekor Abu Bakar yang berjalan terlebih dulu.
Mereka berjalan ke arah yang berlawanan dengan orang-orang itu. Abu Bakar mengajak Rasyid melihat pohon asam yang berada di ujung lahan. Pohon asam itu sedang berbuah lebat. Ia akan mengambil beberapa polong yang sudah matang untuk keperluan bumbu dapur. Istrinya telah mengingatkannya sejak beberapa hari itu, tapi Abu Bakar selalu lupa.
Ketika musim kemarau panjang seperti itu, biasanya pohon asam memang berbuah lebat. Meskipun begitu, Abu Bakar hanya mengambil seperlunya saja. Ia membiarkan siapa pun yang tertarik untuk mengunduhnya sendiri, selama dalam batas yang masih wajar. Maka tidak heran, jika pada suatu hari, terlihat seseorang membawa galah sedang memburu berpolong-polong buahnya yang terasa masam-manis itu.
Hanya saja, Abu Bakar tidak akan pernah mengijinkan jika melihat seseorang berdiri di bawah pohon asam dan kencing sembarangan di sana. Ia pasti akan menegurnya dengan keras. Pernah suatu kali, ia nyaris tidak bisa menahan diri ketika mendapati seorang pemuda dengan seenaknya mengencingi pohon asam yang telah ditumbuhkan dengan susah payah oleh mendiang ayahnya itu. Kalau saja dia tidak sedang bersama Rasyid, mungkin situasinya akan berbeda. Demi memberi pelajaran kepada pemuda itu, ia melarangnya mengambil buah asam yang sudah di depan mata.
“Kau ingat, sewaktu aku marah dan menegur seorang pemuda beberapa waktu lalu?” tanya Abu Bakar ketika mereka sudah sampai di bawah pohon asam itu.
Rasyid mengangguk pelan. Ketika mengingat apa yang dilakukan pemuda itu, ia segera merasa tertuduh. Bagaimanapun, ia telah berusaha keras menyembunyikan sebuah rahasia, bahwa dirinya juga pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pemuda itu. Hanya berselang sehari sebelum pemuda itu dipergoki oleh ayahnya, ia sudah terlebih dulu kencing di bawah pohon asam itu.
“Ini tempat yang sejuk dan rindang. Orang-orang yang kebetulan melintas di dekat sini akan menyempatkan diri berteduh. Apalagi musim seperti ini. Bayangkan, seandainya tempat ini bau pesing. Alangkah tidak nyamannya!
“Kau tahu, aku bahkan pernah memergoki seseorang—sepertinya seorang penggembala—tertidur lelap di sini. Aku yakin dia sangat kelelahan waktu itu. Bayangkan, apa yang akan terjadi kalau seandainya tempat ini bau air kencing?
“Jadi, kau tahu sekarang betapa tidak bermartabatnya kencing sembarangan itu,” jelas Abu Bakar seraya duduk dan menyandarkan kepalanya pada batang pohon asam itu.
Angin berembus tenang. Matahari sedikit condong ke barat. Di luar naungan pohon asam yang rindang itu, warna tanah masih terlihat kering dan tua—kecuali pada bagian yang ditumbui semak rumput belulang. Lamat-lamat Rasyid mengingat, kakeknya pernah mengatakan padanya bahwa untuk mengobati sementara anyang-anyangan, ia bisa mengikat jempol kakinya dengan batang rumput belulang. Rasyid pernah mencoba melakukannya, tapi ia tidak ingat apakah itu bisa berfungsi dengan baik. Yang jelas, ayahnya tidak pernah mengatakan hal semacam itu kepadanya.
Rasyid menguap panjang. Ia melirik ayahnya yang memejamkan mata dan tampak tenang. Sepertinya ia juga akan tertidur barang sejenak.
* * *
Sebelum membuka ritsleting celanannya, Rasyid menengok ke kiri dan ke kanan—ke segala penjuru—untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain di tempat itu selain dirinya sendiri. Lagi pula itu sudah menjelang magrib, kemungkinan besar orang-orang sudah berada di rumah masing-masing setelah seharian berjibaku di luar rumah.
Sisa-sisa hujan yang masih tertahan di rimbunan daun-daun asam, sesekali jatuh menimpa pundaknya. Musim yang basah; dan untuk pertama kalinya di musim penghujan itu, ia menjenguk kampung halamannya. Itu tahun keempat ia menempuh pendidikannya di sebuah perguruan tinggi swasta di kota yang jauh. Pada hari kedua berada di kampung halamannya, ia memutuskan untuk bernostagia. Ibunya menyelipkan sebungkus roti tawar beserta selai kacang yang dibelinya di kota terdekat, juga sebotol susu kuda liar segar hasil perahan sendiri. Rasyid akan seharian berada di tempat itu. Ia telah mengunjungi sumber mata air dan berlama-lama merendam dirinya di sana. Setelah puas dan tubuhnya mulai terasa dingin, ia duduk-duduk di tepiannya hanya untuk merokok. Ia juga mengobrol dengan seorang penggembala yang sedang mengawasi kambing-kambingnya merumput di sekitar lahan milik ayahnya. Tour kecil hari itu berakhir di sekitaran pohon asam yang berada di tengah-tengah lahan. Ia menggelar matras dan tertidur pulas di bawah naungan pohon asam.
Ia terbangun menjelang magrib, dan merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan tubuhnya—sepertinya ia masuk angin. Ia pun bergegas menuju peternakan; ayahnya menunggu di sana agar bisa bersama-sama pulang ke rumah.
Ketika melintas di jalan setapak berbatu di dekat pohon asam yang paling besar dan rimbun itu, ia tidak bisa menundanya lagi. Kandung kemihnya terasa penuh dan ia harus segera mengeluarkannya. Barangkali ia lupa nasihat ayahnya agar tidak pernah lagi kencing di sembarang tempat, terutama di bawah pohon asam. Namun, ritsleting celananya telanjur terbuka dan tidak ada siapa pun di tempat itu selain dirinya. “Aman,” gumam Rasyid seraya melepaskan pandangannya ke rimbunan daun asam yang basah oleh hujan.
Air kencingnya mengucur deras dan ia merasa lega. Ia berpikir akan mengeluarkan sebotol air mineral dari dalam tasnya untuk membersihkan tangannya. Pada saat itulah, sebuah gigitan maut—disertai desis—menyerang pergelangan kaki kanannya. Ia sangat terkejut mendapati seekor ular kobra hanya berjarak sehasta dari kakinya yang terluka. Kobra berwarna hitam itu mendesis dan memipihkan lehernya, seolah bersiap untuk serangan kedua. Jantung Rasyid serasa berhenti berdetak. Tubuhnya limbung setelah sebuah teriakan histeris.
Dua orang penggembala yang mendengar teriakan itu melintas di sana dan melihat tubuhnya yang terkapar tidak sadarkan diri. Kemudian, dari sanalah berita menyebar ke peternakan dan Rasyid harus bertahan dalam ruang ICU di sebuah rumah sakit. Untuk menghindari racun yang terus menyebar dan kakinya yang terancam membusuk, ia harus diamputasi. Tidak ada yang bisa menolak kenyataan, bahwa Rasyid harus kehilangan kaki kanan untuk selamanya.
Hari-hari selanjutnya di bulan itu, adalah hari-hari penuh perkabungan bagi Abu Bakar. Pada suatu hari, ia membawa gergaji mesin dan menghabisi pohon asam di dekat jalan setapak berbatu itu. Lalu pada hari berikutnya gergaji mesin itu meraung-raung kembali di tengah lahan; sebatang pohon asam yang lainnya pun tumbang. Sebatang pohon asam yang mengering karena tersambar petir pun tidak luput dari sasaran. Ia juga membakar semak-semak di sekitar tunggul pohon yang tersisa untuk memancing ular kobra keluar dari sarangnya. Namun, hingga musim kemarau tiba, ia bahkan tidak pernah mendengar desis binatang melata itu.
* * *
“Akulah yang menyetujui ayahmu tinggal di kota untuk memulihkan semangatnya,” jelas Abu Bakar. “Ia kutitipkan pada Kakek Yamin, adikku satu-satunya yang sejak kecil tinggal di kota bersama kakek-buyutmu yang lain. Di sanalah ayahmu berangsur pulih, terutama karena kehadiran seorang perempuan yang akhirnya menjadi ibumu.”
Ahmadi merasa takjub mendengar kisah yang diceritakan oleh kakeknya. Kini ia mengerti, apa yang menyebabkan ayahnya begitu membenci ular. Namun, dari semua yang diceritakan oleh Abu Bakar, ada sebuah detail menarik yang mengusik hatinya, tidak lain adalah tiga batang pohon asam itu. Ia bisa memahami rasa kehilangan bertahun-tahun yang dialami oleh Abu Bakar. Dan ia tahu, satu-satunya cara untuk mengobatinya adalah dengan menumbuhkan pohon-pohon yang baru.
“Jadi, kau sudah tahu sekarang,” ujar Abu Bakar.
Ahmadi tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya manggut-manggut. Abu Bakar merasa lebih lega telah menceritakan kisah yang sebenarnya kepada cucunya. Abu Bakar pun mulai tersenyum. Ia kembali menyerahkan pikirannya ke seluruh bentang lahan yang bisa dijangkau dengan pandangan matanya. Ia membayangkan beberapa ekor kuda atau kambing sedang merumput di sana, lalu sekawanan anak-anak bergantian memanjat pohon asam atau melemparinya dengan ranting kering untuk berburu buahnya yang masam-manis.
“Aku ingat sebuah nasihat,” ujar Ahmadi tiba-tiba. “Kakek pernah mengatakannya padaku.”
Abu Bakar mengernyitkan dahi. Ia tampak sedang mengingat-ingat sesuatu. “Aku pernah mengatakan banyak hal kepadamu,” ujarnya kemudian.
“Kalau tidak salah, seorang yang saleh pernah mengutip apa yang pernah dianjurkan oleh seorang nabi: kita tak dianjurkan membiarkan lahan-lahan mati,” tanggap Ahmadi. “Kakek telah berusaha menghidupkannya. Itu salah satu yang paling kuingat.”
Abu Bakar kembali mengernyitkan dahinya, lalu seutas senyum mengembang di bibirnya.[]
Ampenan, 20 Oktober 2020-2 Februari 2021
Penulis:

Tjak S. Parlan lahir di Banyuwangi. Cerpen dan puisinya sudah disiarkan di berbagai media. Bukunya yang sudah terbit: Kota yang Berumur Panjang (Kumpulan Cerpen; Basabasi, 2017), Berlabuh di Bumi Sikerei (Feature Perjalanan; Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2019), Sebuah Rumah di Bawah Menara (Kumpulan Cerpen; Rua Aksara, 2020). Selain menulis, sehari-harinya mengerjakan ‘perwajahan’ untuk sejumlah buku dan sejumlah penerbitan. Saat ini mukim di Ampenan, Nusa Tenggara Barat.