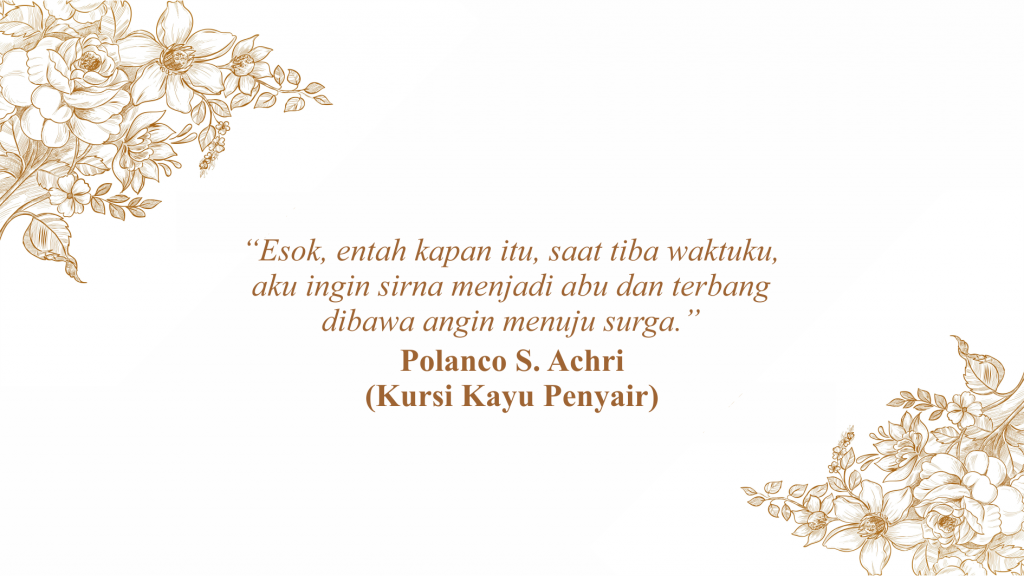
Kursi Kayu Penyair
DI hadapan kenangan, manusia selalu menjadi sesuatu yang pecah dan retak—dan barangkali hal itu juga terjadi pada diriku. Ah! betapa seharusnya aku memperkenalkan diriku terlebih dulu. Aku adalah sebuah kursi kayu, yang sangat sederhana. Sebuah kursi kayu yang menjadi teman duduk, dalam arti yang sesungguhnya, dari seorang lelaki—yang kutahu bekerja sebagai seorang penyair. Ialah yang memberi nama Aros.
Penyair itu pernah membaca bahwa dengan menamai benda-benda akan mengangkat benda itu dari suatu kegelapan yang dalam—yang juga kurasakan. Penyair itu merasa dirinya sebagai Adam; dan entah mengapa aku menyukainya; dan hal itulah yang membuatnya merasa memiliki suatu kewajiban untuk menamai apa-apa.
Masih kuingat saat pertama kali bertemu dengannya . . .
Aku ada di sudut dari toko kecil yang menjual mabel. Saat itu dia masihlah muda, seorang lelaki dengan rambut yang agak panjang dan dengan pakaian yang cukup rapi: celana jin dan kemeja lengan panjang yang lengannya digulung.
“Pak, kursi ini harganya berapa?” tanyanya.
Pemilik toko yang juga pembuatku itu berkata, “Murah, Mas, lha ini hasil kerja saya pas kurang bagus.”
Keduanya tersenyum dan tertawa sesaat.
“Kalau begitu, saya akan ke sini lagi empat bulan dari sekarang, Pak. Saya akan beli kursi ini,” katanya sambil sedikit tertawa. “Jadi jangan dijual dulu, ya, Pak.”
Setelah berkata begitu, ia pergi, dan pemilik itu berkata—padaku: “Pemuda yang menarik. Kuberikan pun bukan suatu masalah; tapi hal itu akan menyakitinya, sebab dikasihani adalah kebaikan yang menyakitkan.”
Diam-diam, tanpa kusadari, aku jadi menunggu kedatangannya. Sebab, memang, siapa pula yang mau membeli kursi semacam aku di zaman yang katanya sudah terlalu maju. Ah! dan benar kiranya, dia datang tepat empat bulan dari pertemuan itu. Setelah basa-basi, dia segera membayar dan membawaku—dengan berjalan kaki—menuju ke kontrakannya: sebuah bangunan kecil yang ada di pinggir kota.
Aku diletakkan dekat jendela, berhadapan dengan meja—yang sebenarnya adalah rak buku—yang dibuatnya dari peti buah! Betapa ruangannya hanya berisi buku, buku, dan juga buku, di samping beberapa kertas hasil ketikan atau tulisan tangannya.
Selain itu, ada lemari kecil yang isinya hanya beberapa pasang pakaian, pakaian yang sama sederhanannya dengan yang dipakainya saat pertemuan pertama itu. Ah! iya, ada pula sebuah mesin tik; mesin tik yang dinamai Luna oleh si penyair. Dan, dari Lunalah aku tahu, apa-apa yang dilakukan empat bulan olehnya sampai akhirnya berhasil membeliku. Ia menulis, dan menulis, dan mengirimnya ke koran atau majalah; semua itu dia lakukan sambil berdiri—seperti pengarang kenamaan luar negeri yang juga menjadi idolanya.
Aku menemaninya menulis dan membaca; dan, sedikit-banyak, karenanya, aku hapal pada buku yang dibacanya: beberapa disanjungnya, beberapa yang lain dikatakan buruk, dan beberapa lain dalam jumlah yang lebih sedikit ingin dilampauinya. Ketika menemaninya menulis, sering teringat olehku saat masih menjadi sebuah pohon, menjadi bagian dari sebuah pohon. Saat itu aku pernah bercita-cita menjadi tongkat Musa, atau bagian dari bahtera Nuh. Akan tetapi, semakin hari, semakin bersamanya, aku pun semakin senang menjadi kursi dari seorang penyair. Sesekali, dia pergi ke luar kota; sempat pula dia ke ibu kota; dan di saat begitu, aku merasa apa yang disebut rindu. Ah! puisi memang menjadikanku makin manusia.
Ia juga cukup sering menabung, meski sering juga dipecahkannya tabungan itu untuk kebutuhan sehari-harinya. Namun, akhirnya, ia berhasil mengumpulkan uang dan memberanikan diri melamar seorang perempuan—yang menerima jalan hidupnya, jalan sebagai seorang penyair. Betapa menarik mahar yang diberikan untuk istrinya: setumpuk buku puisi terjemahan! Itu mungkin aneh, tapi begitulah dia. Hari-hari makin menyenangkan setelah itu, meski aku juga menjadi saksi dari kebutuhan dan perubahan zaman yang kian mendesak. Ah! amat sesak—membayangkan itu di benak.
Manusia hanya bisa menerima, dan itulah yang pasangan itu lakukan. Mereka tak bisa memiliki anak. Tetapi, betapa istri penyair itu amat setia; bahkan dia berkata, “Katamu, puisi adalah anak yatim setelah dilahirkan penulisnya. Maka, aku akan merawatnya. Bukankah Tuhan dan Nabi meminta kita untuk menyayangi anak yatim? Aku akan merawat mereka, Mas.”
Ah! betapa hari-hari selalu dipenuhi puisi dan puisi. Hingga, akhirnya, mereka sepakat merawat seorang anak lelaki yang ditinggalkan bapak-ibunya—yang adalah kerabat dari istri penyair itu. Suatu episode tergambar jelas dalam ingatanku: Penyair itu memangku anak asuhnya, dan mengajarinya mengetik nama-nama rasi bintang, sedangkan istri penyair itu memandangi suami dan anak asuhnya: teramat senang.
Zaman terus berubah, tetapi lelaki itu masih setia pada Luna, mesin ketiknya, dan tetap memakaiku untuk duduk—meski pernah ada yang menawarinya kursi yang lebih empuk. “Kursi ini adalah teman duduk yang baik, aku tak bisa mengganti teman yang baik,” ucap lelaki itu, yang mana ucapan itu selalu membuatku terharu saat mengingat-ingat.
Lelaki itu juga kuanggap amat luar biasa; betapa dengan hidup dari jalan menulis, dirinya bisa menghidupi anak dan istrinya—meski dirinya selalu, dan terlalu sering, berpuasa. Anaknya selesai sekolah menengah atas. Lalu, dengan uang hasil menulis lelaki itu, anaknya melanjutkan belajar ke perguruan tinggi ditambah beasiswa yang berhasil didapat si anak.
Tentu banyak episode yang teringat, tetapi ada sebuah peristiwa yang akan selalu terkenang. Yaitu: saat istri sang penyair meninggal. Ah! ia kian rajin termenung. Sebuah buku puisi terlahir—sebelum dirinya terkena penyakit. Dan aku masih tak tahu apakah kesepian adalah penyakit atau bukan. Akan tetapi, tak lama sesudah itu, ia pun sakit keras; dan suatu ketika, ia berkata pada anak asuhnya: “Nak, mungkin sudah waktunya Bapak menemani Ibumu di Surga. Aku minta kaurawat kursi, mesin tik, dan segala yang Bapak punya meski tak banyak.”
Anak itu paham dan tak menyela ucapan si penyair itu. “Semoga, di Surga, Tuhan mengizinkanku untuk menulis puisi,” tambahnya setelah terdiam sesaat.
Beberapa hari setelah berwasiat, penyair itu akhirnya pergi meninggalkan kenangan. Anak itu membawa segala barang milik bapak asuhnya dan menempuh jalannya sendiri. Ia membeli rumah kecil di dekat sebuah toko buku bekas. Ia sudah menikah dan istrinya mengandung tujuh bulan.
Luna, mesin tik itu, masih dipakainya mengetik ketika malam Jumat. Dan selain saat-saat itu, biasanya ia mengetik memakai laptop yang dibelinya dengan harga murah. Penyair itu pernah bilang pada anak dan istrinya, bahwa surga itu tempat yang penuh dengan buku; dan sebab itulah Tuhan berfirman: Bacalah!
Esok, entah kapan itu, saat tiba waktuku, aku ingin sirna menjadi abu dan terbang dibawa angin menuju surga. Tak lain, agar bisa menemani penyair itu membaca dan menulis puisi di sana; Luna pun berharap bisa menemani si penyair itu untuk menulis puisi di sana.
Ah! semoga Tuhan yang Mahasunyi itu, yang suka menunggu, berkenan mengabulkan pinta sebuah kursi tua ini.
Amin . . .
(2018—2020)
Penulis

Polanco S. Achri lahir di Yogyakarta, Juli 1998. Tinggal di Yogyakarta pula. Lulusan jurusan sastra dari sebuah kampus negeri di Yogyakarta. Seorang tukang tulis naskah lakon dan cerita di Komunitas Utusan Negeri Dongeng. Di samping itu, menulis puisi dan esai-esai pendek yang tersebar di media, baik yang daring maupun cetak. Dapat dihubungi di FB: Polanco Surya Achri atau Instagram: @polanco_achri.
Keren…