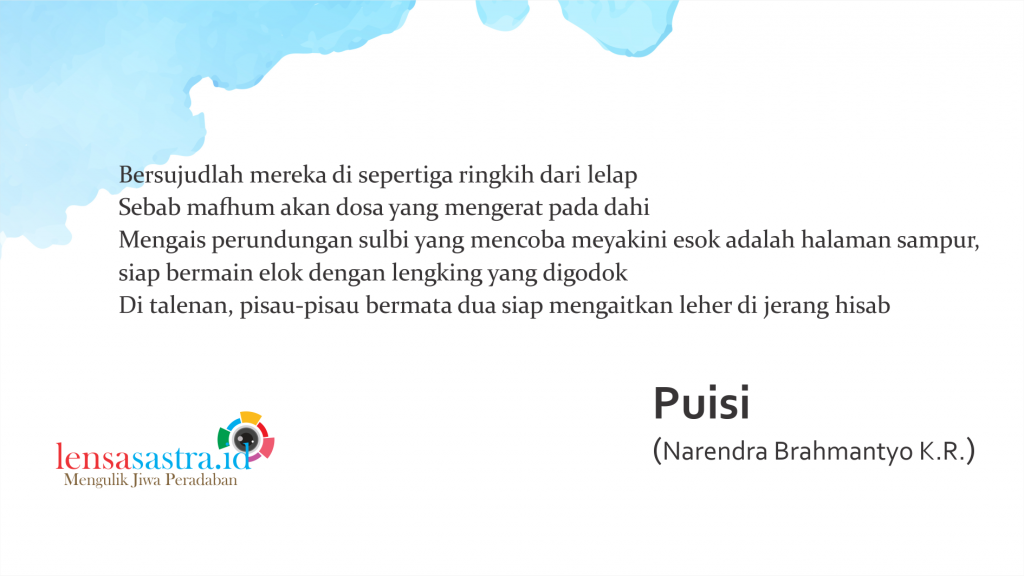
Puisi Narendra Brahmantyo K.R.
Di Usia Lekang Ini
Segera, kita beranjak pada peralihan tentang anak-anak dan noda malam yang meluberkan upaya-upaya kelam dari doa di ujung jemari.
Kita tak perlu menanti kepandaian: berhitung bintang yang memagari kepungan kabut. Kita hanya masih memakai hari – dicium kening – memanjat tubuh ijazah.
Kita barangkali lupa menata kembali buku-buku paket berisi tebusan usia
Sebab kita hanya sibuk mencatat dan mengisi bangku-bangku kosong tempat kita bercerita
Menanti suap-suap kabar; mengurai pelajaran-pelajaran seperti mengundi nasib kecerobohan memerankan puisi
Sayup-sayup mata mengembang. Tubuh-tubuh menadah. Aku bertekuk sungging, ingin menghapuskan kerontang. Kau tak perlu meraba sejauh mana dosa telah mengapur.
Di usia lekang itu, terus kucoba mengayuh laju, supaya nantinya kita membangun kediaman baru: kau membaca malam-malam panjang, mengepulkan kembali doa-doa, menghitung usia-usia sajak dan perawian bintang, dan kemudian tidur diselimuti awan mendung atas mataku.
Namun di usia lekang ini, kau menguliti pelepah pulang
Getahnya berbekas, aku berpaling sekejap menaruh lengan – membela pundakku.
Semenjana sudah raga ini, kau memulangkan tabah dan aku dijajah air mata
Gombong, 10 September 2021
Esok Selagi Bisa
/1/
Daun kering hinggap di seberang mata, menutupi kongsi semut dari tumpah kesedihan langit
Lajurnya terpaksa memutar, mereka takkan pernah tahu kapan semua ini usai
Sebab usaha sungut adalah penghabisan, merayap pada jejak-jejak yang kini mengungsi bersama
Bebal sudah sepundak makanan tergusur mengingat setipis pasrah tak boleh kumal.
Esok selagi bisa
Mereka tidur pada selimut kabut
Setangkap demi setangkap mereka mengurung derasnya lajur dengan jatah makan malam
Janji-janji menguar di petang: rahang siap menganga; mengiba langit kembung tatkala rahang mengaba siap menidurkan lambung
/2/
Jejak peribadatan terpanjat mengisi desing
Malam melarutkan iba, deras-derasnya kini tersapu sebab tasbih sulit didengar jika kesedihan meraung tragedi manusia. Ya, manusia.
Di seberang, ke rumah manusia, selembar koran baru saja selesai dibaca sesaat rembesan hujan mengetuk seduh kopi.
Geger sudah raut wajah menyiapkan pundi-pundi serapah. “Sampai kapan aku harus bermukim? Tuhan Maha Tidak Adil!”
Sampai malam berlarut, memarut hasta kening berkerut, manusia itu memagari mata pada halaman yang kini telah meluap. “Esok selagi bisa.”
Raga yang telah patah masih berusaha menghabiskan gelas-gelas puisi di pematang tahun ini
Ia hanya ingin pembenaran, sebait saja.
Lalu ia buang jauh-jauh beberapa lembar yang pecah
Ia kumpulkan ironi sarkastik untuk ditenggaknya seorang diri, berharap bisa mabuk selekasnya
“Aku ingin,” dan sebab-sebab manusia lain ia makzulkan, “aku harus,” segera, esok masih harus ia pungut kursi perjanjian.
/3/
Kembali, di seberang manusia, kongsi semut telah bersiap pergi
Mereka canangkan lembar-lembar puisi buangan itu sebagai kapal menuju pelabuhan baru: rumah manusia
“Esok selagi bisa.” Mereka ingin menghimpun diri pada kursi, tempat remah-remah lambung manusia itu tertinggal.
Gombong, 26 Oktober 2021
Jalan Menafkahi Peradaban
/1/
…wa rattilil-qur`āna tartīlā;
Santri-santri di pedepokan zaman bertartil di pematang dahan
“Marratan,” berbaik saleh menyulam laman
: ayat-ayat yang diemban di batin sepinggan-sepinggan
Bersujudlah mereka di sepertiga ringkih dari lelap
Sebab mafhum akan dosa yang mengerat pada dahi
Mengais perundungan sulbi yang mencoba meyakini esok adalah halaman sampur, siap bermain elok dengan lengking yang digodok
Di talenan, pisau-pisau bermata dua siap mengaitkan leher di jerang hisab
/2/
Pada benteng terakhir, peradaban kumuh mengisi harapan masyhur yang tertugur
Maka orang-orang saleh kabur
Melemburkan kapur;
Menggurat rapuh papan langit semenjak siang telah berlumur, wajah nan kufur
“Siang tak pernah gusar melelahkan dan malam tak pernah gusar menyuruh tidur.”
Kiai pada suatu kala masih terasa duduk menghadap pasang wajah santri-santrinya
“Maka bangunlah benteng di dadamu sebagai tempat orang-orang bernaung dari bahaya dunia.”
Mendekaplah pada salah seorang yang mencoba bertamu pada Lauhul Mahfudz, tatkala ia masih mengiris doa di kuyup sajadah
/3/
Jeritan-jeritan pasi di itu bermula memungut orang-orang iba
Sementara penghuni asrama seolah membanting kamuflasenya
Berbiak runyam, merebut pucat ruangan.
Itu adalah santri kelas awal
Seringkali batin dibubuhi perkampungan lahad sebagai tempat orang tua menafkahi jarak
Rumah adalah kekosongan pikiran
Wejangan adalah lelap yang mengarak
Sementara wajah adalah kompor yang telah dipanaskan berhari-hari, telah siap untuk menanak kehidupan
Gombong, 22 Oktober 2021
Membaca Golongan Merdeka
Kibarkan saja dada, dan sebiji penantian tak lagi merongrong pada daur ulang segala yang malfungsi dari ranah merdeka kepunyaan tanah sendiri
Pribumi tak lekang akan seberkas golongan muda dan tua, menaruh harap tentang upacara hikmat pada tiang bambu setegar proklamasi
“Segera, laporkan! Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saksikanlah. Nippon tengah berduka. Sampai kapan kita terus tidur di teras rumah sendiri sedang di dalam hanyalah berisi kekosongan? Kita harus mendobraknya!”
Maka golongan muda kian moncer memahat surat-surat kabar. Para pengangguran pun layaknya jurnalis, menyurat mulut ke mulut; menawan duka, “merdeka ataoe mati, bersatoe, merdeka!” Sebab alat perang tinggalah mural dilukis bambu runcing; di tetes-tetes pakaian karung goni.
Golongan tua tinggalah diam, menganggurkan esok. “Darah masih harus dikepal seorang-seorang.”
Tapi namanya Nippon tak ubahnya akan segera cair, golongan muda segera mengikat bujuk, “mereka masih akan menumpahkan darah di rumah kita.”
Segeralah golongan tua menyingkirkan penat, “esok selagi bisa,” lembah-lembah temaram kian dekat di ujung waktu, “pertemuan kita yang singkat, esok kita mulai bersiap.”
Tapi esok bukanlah menjadi sebiji penantian. 16 Agustus 1945, golongan muda telah siap memanaskan mesin demi meraih golongan tua. Bertolaklah mereka menuju Rengasdengklok seraya menyusun harap. “Nippon pembohong.”
“Segeralah esok. Pulangkan kami ke Jakarta maka akan kami susun proklamasi. “Selambat-lambatnya esok, potong saja leher ini jika esok proklamasi hanya seutas kosong.”
Golongan muda melunak. Segeralah mereka kembali.
Benarlah waktu itu 17 Agustus 1945, sepasang warna mengibas
Jurnalis-jurnalis mendekat, membingkai prasasti dalam cetak massa sesaat Bung Karno mulai bertapak. Ditanggalkanlah malaria yang tak ingin menjangkit sila-sila kemerdekaan di tubuh baginda bangsa. Segera, sepatah kata mulai menjunjung negeri dari sejarah kelam, membuang jauh-jauh serpihan koloni. “Proklamasi…”
Gombong, 2021
Pengibadahan Sakit
Kini, kita bukan lagi sesiapa selain remah-remah
kejam yang mengeja tebing dada di pengibadahan sakit, tak pernah lupa tentang tubuh setegar abu menata cerita akan cengkeraman kediaman silam
Seperti menjaja cakap, kita tak pernah berpuas untuk bermadu pikir
Kelayapan di tengah auman anak-anak sekitar surau, mengingat kembali lengking bujuk sesepuh yang tangannya letih mengaduk peluh
Doa-doa panjang kita pusingkan kala itu dekat daun sajadah yang memangku pasang toa akan asma kehidupan
Enggan sekejap menengok pada lembayung–percaya sakral itu telah terpasung: hilal menyayat degup peribadatan atas pangkal Hijriah yang mengacung
Kita pernah membaca pahit yang wajahnya selalu menerka usia
Sedang kini, raut tampang berbaur lembah-lembah lembayung
Menenggak kopi; menyingsing pekat raga.
Kita pasang wajah-wajah di gerai sosial
Berkutip pesakitan tabah
Gombong, 16 September 2021
Waktunya Mengubur Separuh Arterimu
/1/
Sebelum kaujahit kain perca di mejamu, tempelkan iba seorang ibu tentang bagaimana ia mengenakan lusuh corak-corak kulit peninggalan sepatah raga yang mengungsi di benakmu
Sebab tidur lelap seringkali mengingatkan caramu memahami dongeng-dongeng yang dibacakan menuju kerunyaman sunyi
Sampai kau berada di jalan-jalan lengang pada sebatang mimpi; ingin mengendarai wajah-wajah tak jelas yang bertengger di tengah jalan, kaulihat seseorang berdiri sibuk menatapmu di jeda lampu merah, memasang ubun-ubun yang macet dengan lalu lintas iba
Barangkali kau tak peduli, sebab kau selalu membuang tampang berlagak mencari seberang gender: pada rumpang wajah-wajah belia.
/2/
Sebelum kaukenakan corak lusuh kulit ibumu, rampungkan tagihan-tagihan pasi di jenjang raga tentang sebilah senyuman yang urung kaugarap di jagat kefasikan hari
Derita seringkali kau bicarakan
Tragedi-tragedi kauungkit menyusup kosong patah hati
Kau hanya ingin seseorang datang dari belakang, membuntuti kisahmu, mengecam derita orang-orang kalah pada suatu hari yang mereka relakan, sedang kau tidak.
Kau ingin layar kaca mengabadikanmu: metafor kaya akan lebam-lebam di surat yang kaupahat seorang diri merundung babak-babak retisalya; mencoba menyingkir dari kepala puber. Segera, sebelum usia beranjak nadir.
/3/
Sebelum sebilah senyuman kaugarap, rampungkan urusanmu pada harap; di hadap tangis seorang penyadap; di tangis seorang pemantik kisah yang terlelap.
Kau urung tiba tahun ini: bersantai mencium kening, menjemur kabar, dan mencuci peluk di corak wajah peninggalan ibu.
Gombong, 3 Oktober 2021
Penulis:

Narendra Brahmantyo K.R., seorang mahasiswa baru di Universitas Ahmad Dahlan dengan nama asli Narendra Brahmantyo Karnamarhaendra Roosmawanto. Tempat kepulangan di Gombong, Kebumen. Berpuisi, menulis novel di sebagian waktu. Kutipannya bisa dilihat di Instagram @nareend__, dan Twitter @Narendra_BKR
Selamat dan sukses selalu ya Rendra 👍👍