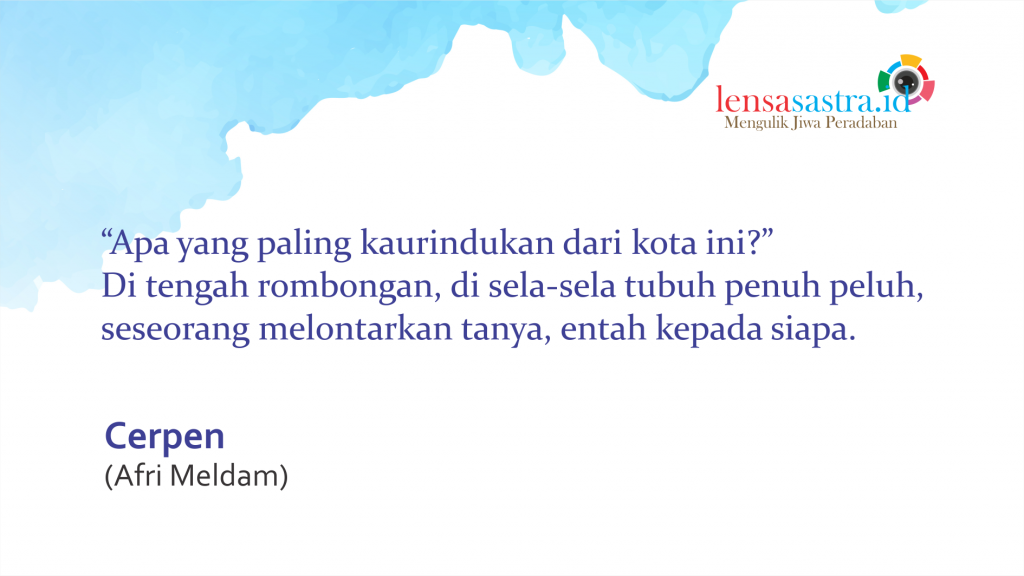
Seusai Perang
“Apa yang paling kaurindukan dari kota ini?” Di tengah rombongan, di sela-sela tubuh penuh peluh, seseorang melontarkan tanya, entah kepada siapa. Dan, memang, setelah beberapa menit berlalu, tak ada seorang pun tergerak untuk memberikan jawaban.
Mereka, pemuda-pemuda dari Mayaqa yang dulu bergabung dengan pasukan militer di perbatasan, kini telah kembali, membawa cerita dan luka masing-masing. Jaq kehilangan sebelah telinga. Rou masih berjalan dengan bantuan kruk. Doz sudah tak bisa lagi mendengar dengan baik. Mat sudah sepenuhnya bergantung pada kursi roda. Sementara Gail, Liv, Mal, dan Iku, yang dulu berangkat bersama mereka ke perbatasan telah menjadi penghuni ruang kenangan.
Orang-orang tua, para perempuan, dan anak-anak juga telah kembali ke Mayaqa. Mereka langsung meninggalkan hutan di Utara begitu mendengar bahwa perang telah usai. Tentu saja rindu dendam akan anggota keluarga yang maju ke medan pertempuran telah menggerakkan kaki mereka lebih cepat, menggumamkan doa-doa sepanjang jalan, menyongsong orang-orang terkasih dengan pelukan.
Beberapa dari orang tua dalam rombongan itu tentu menumpahkan airmata karena tak berapa lama lagi mereka akan mendengar kabar tentang anak-anak mereka yang sudah gugur sebagai martir. Meski ketika anak-anak mereka pergi ke perbatasan dulu semua kemungkinan terburuk sudah dibayangkan, begitu kabar duka disampaikan, sebagian menangis histeris, menumpahkan segala perih lara, berguling-guling di tanah, atau memanggil-manggil nama anak atau cucu tercinta dalam ratapan mereka.
Fami, perempuan tua yang berjalan di barisan depan, mungkin akan menangis sejadi-jadinya begitu mengetahui bahwa Gail, putra bungsunya telah bergabung bersama syuhada lainnya di surga. O Gail yang malang, kenapa kau tak ikut saja bersama kami bersembunyi di hutan, Nak? Kenapa kau harus pergi memanggul senjata bersama pemuda-pemuda lainnya ke perbatasan? Kau anak satu-satunya yang masih kumiliki, kepada siapa lagi segala keluh kesah akan kuceritakan? Siapa lagi yang akan melanjutkan keluarga kita, Nak? O, Gail, anakku, kenapa tak kaubawa saja aku ikut bersamamu ke perbatasan? Aku akan melindungimu dari para musuh yang tak beradab itu!
Nenek dan kedua orang tua Liv, yang hanya berjarak beberapa langkah di belakang Fami, mungkin juga akan berbuat hal serupa. Salah satu dari mereka mungkin akan menjatuhkan badan ke tanah begitu nama cucu dan putra kesayangan mereka telah menemui ajal di medan perang. Mereka mungkin akan menyampaikan kepada orang-orang tentang betapa Liv yang pintar tak seharusnya mati seperti itu. Bahwa Liv seharusnya berangkat ke pusat kota, berbekal pena dan buku-buku, menimba ilmu di salah satu universitas terbaik untuk mewujudkan impiannya menjadi seorang dosen.
Ayah Mal yang sudah rabun, yang duduk di dalam gerobak kuda bersama beberapa pengungsi lainnya, mungkin tak akan bisa meneteskan airmata ketika seseorang membisikkan kabar kematian itu ke telinganya. Mungkin ia hanya akan terpekur, mengirimkan doa-doa untuk anak tercinta. Atau bisa jadi ia juga akan membayangkan hari-hari terakhir ketika Mal masih bersamanya. Begitu perang usai, Mal berencana membuka kembali toko roti keluarga yang dibakar pasukan musuh. Perang memang biadab, segala kesepakatan tak pernah diindahkan—mungkin ia akan mengucapkan lagi kata-kata itu. Apa tujuan mereka membakar toko roti dan menjatuhkan bom di pusat-pusat perbelanjaan kalau bukan untuk melumpuhkan kota?
Orang tua dan saudara-saudaran Iku, yang dalam barisan para pengungsi itu berada agak jauh di belakang, mungkin saja akan bersikap lebih tenang, demi mengingat bahwa pemuda itu memang bercita-cita menjadi tentara dan telah lama menantikan panggilan untuk bertempur. Ketika akhirnya Iku menemui ajal di medan perang, dengan jasad yang tak bisa lagi dikenali, mereka tentu akan menerimanya dengan kesadaran bahwa pemuda dari keluarga mereka telah menunjukkan bakti kepada bangsanya. Namun, kesedihan tetap menyelimuti hati mereka semua.
Hati yang harus tetap dikuatkan setelah perang tak menjadikan satu pun dari mereka sebagai pemenang. Kota mereka telah menjadi abu, kota musuh telah menjadi arang.
Rumah-rumah telah hancur. Gedung-gedung tinggal puing. Kantor-kantor pemerintah rata dengan tanah. Sejauh mata memandang, hanya terlihat tumpukan abu, pohon-pohon kering kerontang, dan puing-puing yang malang melintang.
Perang yang berlangsung berbulan-bulan tak hanya meluluhlantakkan kota mereka. Kota di pihak musuh pun telah dibuat hancur lebur. Ketika satu bom dijatuhkan di kota mereka, serangan balasan segera dilancarkan. Begitu seterusnya. Hingga, ketika gedung-gedung pemerintahan, pangkalan militer, markas polisi, dan bangunan-bangunan strategis telah dihancurkan, kedua belah pihak mulai menyasar kawasan permukiman. Gedung sekolah, perpustakaan, rumah sakit, tempat ibadah, restoran, universitas, toko-toko, pusat perbelanjaan, rumah-rumah penduduk, tak satu pun luput dari serangan rudal dan terjangan bom. Mayat-mayat bergelimpangan, jerit tangis memenuhi rongga telinga, api berkobar dan asap membubung di mana-mana.
“Tolong, hentikan perang ini,” orang-orang memohon.
“Kita semua telah kalah. Kita semua telah hancur!” teriak yang lain.
“Apa kita semua harus mati dengan cara seperti ini?”
“Tidak cukupkah ribuan nyawa yang telah melayang akibat perang yang tak berkesudahan ini?”
Namun, perang terus berlanjut. Korban terus berguguran. Kota terus digempur hingga hancur. Siang malam pesawat-pesawat tempur memenuhi langit. Tank-tank merangsek ke pusat kota. Dokter dan paramedis di tenda-tenda darurat tak bisa lagi merawat orang-orang yang terluka. Kantong-kantong darah tak pernah cukup. Obat-obatan selalu kurang. Anak-anak yang tak bisa lagi menghabiskan hari-hari dengan bermain kini menjerit di tempat-tempat pengungsian.
Hingga kedua pihak merasa lelah. Hinga kedua pihak menyadari betapa perang tak penah benar-benar menjadi jalan penyelesaian. Kota yang mereka perebutkan telah menjadi tumpukan puing, sementara orang-orang yang mereka cintai telah ikut terkubur di dalamnya.
Mayaqa yang terkenal dengan kota tua yang cantik dan universitas-universitas berusia ratusan tahun kini tak lebih hanyalah reruntuhan beton dan padang abu. Lubang serupa danau kering menganga di mana-mana. Jutaan buku di perpustakaan universitas telah menjadi serpihan debu yang menempel di pecahan tembok, kaca, dan pohon-pohon. Balai Kota dengan alun-alun yang dipenuhi burung merpati kini hanya menyisakan kepingan bata, tumpukan pasir, dan pecahan ubin. Dan, burung-burung merpati itu, ke manakah mereka pergi? Lalu, sejak kapan pula gagak-gagak buruk rupa dengan paruh runcing dan kaok yang mengerikan itu datang memenuhi penjuru kota?
Bandara yang dulu ramai kini tak lebih hanyalah dua landasan pacu yang rengkah di mana-mana. Gedung terminal ambruk, menjadi patahan beton tak berbentuk. Pesawat-pesawat di hangar telah sepenuhnya menjadi onggokan besi raksasa dengan lubang-lubang menganga di bagian atap. Menara pengendali yang dulu menjulang di sisi terminal kini terpekur hampir mencium tanah, serupa seorang bujang lapuk yang merana.
Lalu, tengoklah jalan-jalan kota. Bangkai mobil berserakan. Bus ringsek di mana-mana. Sepeda motor remuk patah. Tulang belulang dari orang-orang yang tak sempat melarikan diri ketika hujan bom terjadi di pusat kota masih ada di sana. Menjadi saksi kehancuran kota.
Tak ada lagi rumah-rumah bata merah dengan pot-pot bunga aneka warna yang berjajar di teras dan balkon. Tak ada lagi ruko-ruko bergaya abad pertengahan yang mereka banggakan. Tak ada lagi toko-toko roti, restoran, dan kedai kopi yang dulu menjadi tempat mereka berkumpul setiap sore di akhir pekan.
Tempat satu-satunya yang mereka harapkan kini tentu adalah sebuah bangunan tua bekas pemandian umum di pinggir kota yang luput dari serangan musuh. Pemandian tua itu berada persis di antara dua bukit karang yang menjulang, dan warna bata yang sudah sepenuhnya menghitam menyelamatkan bangunan tua itu dari bidikan pilot-pilot pesawat tempur.
Dan, ke sanalah orang-orang itu kini menuju, membawa asa di dada masing-masing. Bahwa peradaban harus kembali dibangun. Bahwa hari ini adalah mula dari segala harapan yang ada.
“Masih cukupkah anak-anak muda untuk membangun kembali kota ini?” Mereka bertanya-tanya sambil terus berjalan di antara reruntuhan bangunan.
Nun, dari arah yang lain, di tengah rombongan anak-anak muda yang kembali dari medan pertempuran, seseorang kembali melontarkan tanya, “Apa yang paling kaurindukan dari kota ini?”
Hening. Namun, beberapa saat kemudian, seseorang menjawab dengan tegas, “Aku mau tidur dengan tenang!”(*)
~Bekasi, 2020.
Penulis

Afri Meldam, lahir dan besar di Sumpur Kudus, Sumatra Barat. Menulis cerpen dan puisi. Buku kumpulan cerpennya, Hikayat Bujang Jilatang (2015). Noveletnya Di Palung Terdalam Surga (2019) bisa dibaca di Pitu Loka.
Cerpen yang berhasil membawa saya ke alam kesemrawutan perang
dan emosional ketika membacanya, cerpen yang bagus. Mayaqa telah hancur peradabannya akibat dilanda kecamuk pertempuran yang membara🔥