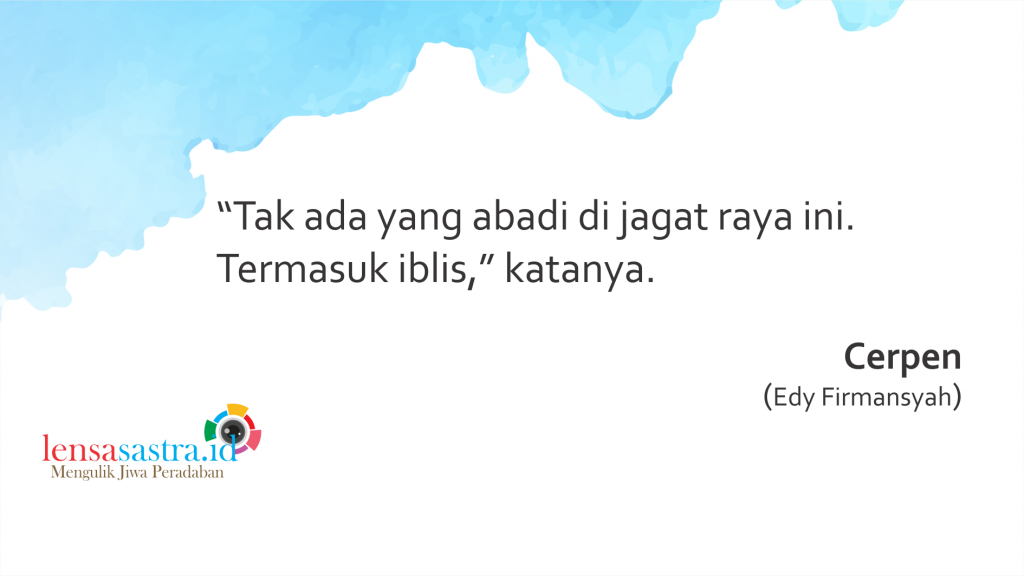
Ruang Isolasi No. 13
Tanganku gemetar menggenggam gunting sunat. Darah menggenang di lantai marmer. Bukan merah. Tapi hijau seperti cairan klorofil. Sebelum defibrilator menyalak bagai ledakan meriam, kulihat sesosok bayangan melompat ke dalam lubang di tembok. Ia meleletkan lidahnya dan mengacungkan jari tengahnya. Ingin rasanya mengumpat, tapi tenagaku telah mampat.
Tapi sebelum sampai pada adegan itu, beginilah segalanya bermula. Akhirnya setelah berkeliling dari kafe ke kafe seperti seorang musafir tanpa mematuhi protokol kesehatan (untuk hal ini aku harus kucing-kucingan dengan petugas) selama masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat saat pandemi Covid-19, aku terpapar juga. Sungguh mulanya aku tak percaya covid itu benar-benar ada. Sama tidak percayanya aku bisa memenangkan judi togel empat angka.
Mula-mula aku terjaring razia swab acak dan hasilnya positif. Sebenarnya aku berhasil melarikan diri. Aku jago dalam hal ini. Tapi entah mengapa saat langkah kaki ke-1001, mendadak paru-paruku macet seperti kelaher yang terlalu lama terpapar air garam. Aku konslet.
Dan disinilah aku sekarang. Terkurung di ruang isolasi di rumah sakit milik pemerintah di kota S, bersama ratusan pasien lain yang dinyatakan positif korona. Sebuah ruangan bertekanan negatif seperti laboratorium dalam film futuristik. Di dinding, terpasang ekshouse dan hepafilter untuk memastikan udara seteril dan sirkulasi udara lancar. Di sudut ruangan, tepat di atas atap, terpasang CCTV untuk memonitor kondisi pasien. Di samping ranjangku terpacak sebuah tombol bel merah untuk memanggil perawat jika pasien membutuhkan.
Sebenarnya adalah sebuah keberuntungan aku bisa berada di ruang isolasi dengan pelaralatan lengkap begini. Kulihat orang-orang bergelimpangan di pelataran rumah sakit saking banyaknya orang terpapar. Mungkinkah aku salah satu orang yang punya peluang hidup lebih besar dari yang lain. Pernah kudengar, karena begitu terbatasnya tenaga kesehatan, orang-orang yang terpapar dan dalam kondisi parah, maka tenaga kesehatan melakukan semacam seleksi alam. Orang yang punya harapan hidup besar lebih dulu diselamatkan. Sedangkan yang tinggal menunggu ajal, direlakan untuk ditangani malaikat maut.
Aku berada di ruang isolasi nomor 13. Konon, kata orang tak ada yang keluar selamat dari ruangan ini. Semuanya keluar sebagai mayat. Di ruangan itu ada sebuah lubang di tembok. Dulu lubang itu bekas selang pembuangan AC duduk. Tapi entah karena AC-nya rusak atau hal lain, AC itu sudah tak ada lagi. Tersisa hanya lubang hitam itu. Aku melihatnya. Seorang pasien pernah berkata padaku bahwa lubang itu bisa mewujudkan kenyataan. Tapi berlaku kebalikannya.
“Jika kau berteriak ke lubang itu ingin sembuh, maka kau akan terus sakit. Jika kau berteriak ingin hidup, maka kau akan mati,” katanya.
Tentu saja aku tidak melakukan apa-apa selama di ruangan ini. Aku tidak perlu meneriakkan sesuatu. Buat apa berteriak ke dalam lubang. Jadi setiap malam aku hanya menatapnya. Sesekali aku mengintip, tapi aku tidak melihat apa pun kecuali kegelapan. Aku mengumpat, “Mitos sialan!”
Malam ketujuh ketika aku mencoba terlelap, lamat-lamat kudengar langkah kaki dari lubang. Segera saja aku turun dari ranjang dan mengintip lubang itu. Mendadak sebuah kepala menyembul dari sana, seolah lubang itu begitu elastis seperti vagina. Kepala itu dua kali lipat besarnya dari lubang itu; gundul, berwarna merah, dan terdapat sebuah tanduk tepat di dahi seperti cula badak. Kepala itu melompat seperti bola meriam yang dilontarkan dan terlihatlah seekor iblis.
Tentu saja aku terperanjat. Tapi tidak lama. Setelah mengatur pikiran, aku mencoba berbicara padanya.
“Aku tidak memanggilmu. Jadi mengapa kau keluar?”
“Aku capek. Di dalam begitu gerah. Aku ingin melihat-lihat sebentar. Mencari udara segar,” katanya sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Iblis itu mungil, kurus dan perutnya sedikit buncit seperti menderita busung lapar. Suaranya serak seolah tenggorokannya dipenuhi pasir. Ia tak banyak tingkah. Hanya duduk di pojok ruangan sambil mengunyah tulang.
Jadilah aku mulai bersahabat dengan iblis itu. Iblis itu suka sekali bercerita. Pernah ia bercerita tentang sekelompok orang tolol yang suka meledakkan dirinya hingga jadi bubur, seolah-olah serpihan tubuhnya bisa bersatu kembali dan melesat menuju surga seperti meteor. Ia menceritakan itu sambil tertawa. “Mereka pikir dirinya akan mati sahid. Padahal, ia hanyalah orang-orang yang kerasukan teman-temanku,” katanya.
Ia juga pernah bercerita tentang surga yang dipenuhi anjing-anjing berpenyakit rabies. Yang membuat penghuninya enggan tinggal di dalamnya dan memilih membuat tenda di depan pintu surga seperti pengungsi atau imigran dari dunia ketiga yang kampungnya baru saja dilanda perang. Kami berdua tertawa terbahak-bahak.
Sampai kemudian tawa kami berhenti ketika terdengar erang kesakitan dari ruang sebelah. Kami merapat ke dinding. Berjongkok. Menguping. Erang kesakitan itu makin panjang diiringi suara kaki menerjang-terjang ranjang. Ranjang berdecit-decit.
Tiga perawat—berpakaian APD lengkap—berlarian. Seorang perawat lain menyusul sambil menyeret dua mesin. Sepertinya alat kejut jantung dan ventilator. Mereka berpakaian seperti astronot. Berlari seperti robot. Tampak berat dan lelah. Tak kudengar napas mereka yang memburu karena wajah mereka ditutupi N95, masker bedah, dan faceshield. Pasien kamar sebelah itu baru masuk kemarin. Aku belum sempat mengenalnya. Tampaknya sekarang sedang kritis.
“Atur posisi syok. Pasang ventilatornya, cepat!” kata seorang perawat yang lamat-lamat terdengar dari kamarnya.
“Tekanan darah?”
“50/30”
“Pulsasi nadi?”
“43x/menit!”
“Pasang dopamine!”
“Sudah!”
“Pasang Jackson ress!”
“Nadinya sudah tak ada!” kata yang lain.
Kemudian sunyi. Hanya deru suara AC terdengar. Detak jam terdengar bagai denting mencekam lonceng kematian. Dua orang perawat keluar dengan langkah lesu. Kepalanya tertunduk. Dua lainnya keluar dengan mendorong ranjang. Seonggok mayat terbaring di atasnya. Pasien di ruang sebelah telah meninggal.
“Kita gagal lagi,” kata perawat yang mendorong ranjang.
“Sudahlah! Tak perlu risau. Semua sekadar angka,” kata yang lain.
Aku mendadak tegang. Jantungku berdegup kencang. Dan segalanya terasa begitu hampa. Segalanya terasa jauh. Yang dekat seolah-olah hanya malaikat maut. Akankah aku mati di ruangan ini? Berakhir sebagai korban virus korona? Berakhir hanya sebagai angka statistik belaka? Kulihat Iblis duduk mematung. Matanya meremang.
“Kau menangis?” tanyaku.
Ia menggeleng sambil mengucek matanya.
“Apakah kau bisa menghidupkan orang mati?” aku coba meredam kalutku dan mencairkan suasana. Iblis menggeleng.
“Daya hidup itu jauh di luar kemampuanku. Jauh lebih ajaib dari kencing iblis. Silahkan saja orang sakit, mengidap penyakit parah yang konon penyakit itu punya pertalian darah dengan malaikat maut, tetapi kalau bukan waktunya mati, dia tak mati mati. Sebaliknya, orang yang kelihatannya baik-baik saja, bisa dikecup malaikat maut. Tanpa pesan. Tanpa tanda yang bisa dibaca. Jadi janganlah berputus asa,” katanya.
Aku nyaris tergelak mendengar pernyataannya. Sok moralis. Ingin rasanya aku berteriak di mukanya dengan dua kata: “Dasar pembual! Dasar toilet neraka!” Tapi aku takut menyinggung perasaannya. Dan aku kehilangan teman yang paling berharga di ruang isolasi ini. Setidaknya karena keberadaannya aku tidak kesepian. Dan perjumpaan seperti ini mahal harganya. Setidaknya jika kisah ini dibukukan, bisa menghasilkan uang. Bahkan bisa menyaingi atau malah melampaui penjualan buku yang ditulis Muhammad Isa Dawud yang judulnya Dialog dengan Jin Muslim. Aku bukan saja berdialog, tapi bersahabat dengan iblis.
Tiba-tiba Iblis melompat dari duduknya dan masuk ke dalam lubang. Mula-mula aku menduga bahwa ada yang salah dari pertanyaanku sehingga membuatnya marah. Tapi ternyata karena ada perawat yang masuk ke kamarku. Ia melakukan tes swab lagi kepadaku. Memasukkan kapas panjang yang mirip sebilah lidi.
“Apakah kalau hasilnya negatif saya bisa pulang?”
“Tentu saja. Kami tak bisa menahan Anda di sini jika semuanya baik-baik saja. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan jika sudah keluar.”
Aku mengangguk. Dan perawat itu berlalu. Sejenak kemudian, ia kembali datang dengan selembar kertas. Dan hasilnya? Masih positif. Kapan penderitaan ini berakhir? Ada perasaan jengkel di dada. Ada yang panas di kepala. Perawat itu pergi.
Tak terasa aku sudah nyaris sebulan berada di ruang isolasi ini. Dan iblis itu belum juga muncul di hadapanku. Berkali-kali aku memanggilnya, berteriak ke lubang hitam I tembok ruang isolasi ini, tapi ia tak juga menunjukkan batang tanduknya. Aku mulai bosan. Mulai jenuh. Dan merasa ingin segera keluar dari tempat sialan ini.
Pada hari ke 84, Iblis itu datang. Duduk di sampingku. Di sisi ranjang. Sambil mengunyah tulang. Tulang anjing.
“Mengapa kau suka sekali makan tulang anjing?” tanyaku.
“Karena aku iblis. Kalau aku zombie, yang kukunyah justru tulangmu,” katanya.
“Apakah kau itu abadi?” tanyaku.
Dia menggeleng.
“Tak ada yang abadi di jagat raya ini. Termasuk iblis,” katanya.
Aku tersenyum.
“Selama kita berteman kau belum menunjukkan kelebihanmu padaku. Bisakah kau menunjukkannya sekali saja?”
“Bisa saja asal jangan menghidupkan orang mati. Aku bisa mendatangkan bidadari surga kalau kau mau. Kuperhatikan penismu mulai tak bisa dikendalikan dan otakmu mulai sering berpikir mesum. Itu lebih halal daripada kau memperkosa perawat,” katanya.
“Bisakah kau mengeluarkanku dari sini?”
“Kalau itu aku bisa,” katanya.
Kulihat matanya berkedip dan tanduknya menyala seperti fosfor dalam gulita.
Mendadak napasku berat. Teramat berat hingga entah mengapa aku serasa kehilangan daya. Jantungnya seolah hendak meledak. Aku pencet bel darurat. Berkali-kali. Tapi tak satu pun perawat datang. Dan iblis itu terus tersenyum sambil mengunyah tulang.
Saat itulah aku sadar telah salah memilih teman. Salah juga mengajukan permintaan. Maka dengan sisa tenaga, aku ambil gunting sunat yang kucuri dari saku perawat dan kutusukkan tepat di lehernya, tepat ketika serpihan tulang itu melewati tenggorokannya. Darah menyembur mirip air mancur, tapi berwarna hijau.
Dia meringis, berteriak kesakitan, dan melompat masuk ke dalam lubang, tepat ketika dua orang perawat datang dan mulai menembakkan defibrilator ke dadaku karena jantungku mogok.(*)
~ Januari-Juli 2021
Penulis:

Edy Firmansyah kelahiran Pamekasan, Madura. Pemimpin umum Komunitas Gemar Baca (KGB) Manifesco, Pamekasan. Buku Kumpulan cerpen terbarunya Yasima Ingin Jadi Juru Masak Nippon (Cantrik Pustaka, Agustus 2021). Esai, cerpen dan puisinya tersebar di banyak media cetak maupun online, di antaranya; Koran Tempo, Jawa Pos, Media Indonesia, Republika, Suara Karya, Suara Merdeka, Harian Seputar Indonesia, Koran Jakarta, Surya, Radar Surabaya, Surabaya Post, Bali Post, Detik.com, kompas.com, basabasi.co, magrib.id, cendananews.com, pojokpim.com, biem.co, apajake.id, story magazine, majalah suramadu, dan majalah Annida. Bisa dihubungi via twitter: @semut_nungging atau IG: @edy_firmansyah.