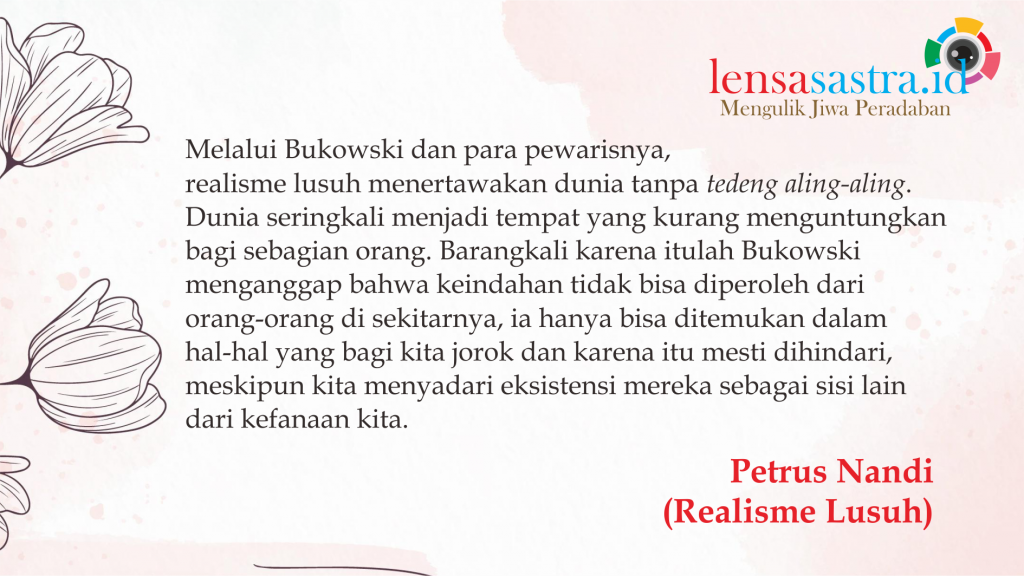
Realisme Lusuh
Aktivitas mengakrabi puisi sudah membawa saya bertamasya ke lorong-lorong yang tak pernah terbayangkan, lorong-lorong yang barangkali muskil bagi orang lain. Ada banyak kenikmatan artistik di sana. Di antara lorong-lorong itu, ada satu yang membuat saya bergidik ngeri, ingin menutup mata, mual-mual dan nyaris muntah. Ya, lorong yang diliputi kotoran manusia, amis usus yang melilit di sebuah pohon dengan seorang manusia berdiri ngap-ngap pada detik-detik terakhir kehidupannya di masa revolusi Rusia, hingga sumpah serapah seorang wanita atas kehidupan yang tak mengizinkannya kencing di mulut kekasihnya. Di ujung lorong itu, seorang penyair dengan paras berjerawat—ia tak begitu rupawan—merayakan kesendirian di antara botol-botol alkohol. Dialah Charles Bukowski, penyair eksentrik dan anti-sosial, yang gemar menertawai kehidupan, ya, lelucon tentang orang-orang yang bersusah payah untuk sekadar bahagia.
Realisme lusuh. Para pemakai bahasa Inggris menyebutnya dirty realism. Itulah nama genre sastra nyentrik, terdepan dalam menampilkan keindahan dari hal-hal yang dianggap sepele, yang remeh-temeh, sebagiannya menjijikkan, yang oleh manusia selalu berusaha untuk dijauhkan. Realisme lusuh adalah antitesis realisme magis, sastra yang berbunga-bunga dan penuh kemegahan itu, yang oleh Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Günter Grass, dan sederetan nama lain itu dirawat tanpa henti. Jika dalam realisme magis orang mengedepankan kolase antara realisme dan unsur-unsur fantastik dengan pola yang terus menerus berubah, serta membangun ambiguitas dengan komposisi yang serius dan yang main-main, realisme lusuh malah mengangkat hal-hal sederhana, yang sering kita temukan, sebagiannya begitu jorok dan seolah seperti aib, jarang dihiraukan sastrawan dari genre lain.
David Wiliam Foster konon menjadi orang pertama yang menggunakan istilah itu. Ia pakai untuk menggambarkan novel gubahan Enrique Medina bertajuk Las Tumbas (1972), sebuah novel yang berkisah tentang kehidupan seorang anak yang ditelantarkan oleh ibunya. Ketika karya-karya Bukowski mengemuka pada periode 1970-an, realisme lusuh acap diidentikkan dengan sosoknya. Ia memang beruntung, sebab setelah melewati masa-masa gelap proses kreatifnya—saat karya-karyanya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang segembel dan sepesakitan dirinya dari kaum hippies dan hobos—orang-orang akhirnya menemukan mutiara di antara kata-katanya yang murung, lusuh, dan cenderung dianggap pesimistik. Demikianlah Bukowski mengudara bersama cerpen, novel, dan puisi yang oleh Aliyuna Pratisti dianggap sebagai gambaran the belly-side of contemporary life. Realisme lusuh menyentak dan menggigilkan realisme magis yang melayang-layang di ketinggian, tak luput pula realisme sosialis yang berseliweran di mana-mana, tak terkecuali Indonesia.
Realisme lusuh adalah gema dari segala hal yang dianggap banal. Dalam banyak kesempatan, kita acap gagal melihat sisi terang dari segala yang gelap, sisi baik dari segala yang dianggap buruk, keelokan dari segala yang dianggap tak elok. Melalui Bukowski dan para pewarisnya, realisme lusuh menertawakan dunia tanpa tedeng aling-aling. Dunia seringkali menjadi tempat yang kurang menguntungkan bagi sebagian orang. Barangkali karena itulah Bukowski menganggap bahwa keindahan tidak bisa diperoleh dari orang-orang di sekitarnya, ia hanya bisa ditemukan dalam hal-hal yang bagi kita jorok dan karena itu mesti dihindari, meskipun kita menyadari eksistensi mereka sebagai sisi lain dari kefanaan kita.
Dalam taraf tertentu, kebahagiaan itu konvensional. Kaum materialis dan hedonis misalnya, sering menganggap diri sebagai orang paling bahagia ketika kebutuhan materi dan segala yang menyangkut kesenangan badani mereka bisa terpenuhi bahkan lebih dari cukup. Dominasi kapitalisme menyihir manusia untuk berjuang menampung profit sebanyak-banyaknya, dan tepat pada saat keuntungan membeludak, orang akan dengan mudah mengklaim diri sebagai yang paling bahagia. Namun, dunia tak pernah memiliki apa-apa selain paradoksalitasnya. Ketika ada yang bahagia karena kaya sekaya-kayanya, ada yang menderita karena miskin semiskin-miskinnya. Kota bernama Los Angeles, tempat Bukowski hidup, tidak hanya terdiri dari bangunan-bangunan megah tetapi juga manusia-manusia gelandangan yang rebah di tanah, tanah yang jorok. Di sisi tempat pesta para konglomerat, ada anak-anak berbadan lusuh nan ceking, melahap makanan basi dengan jari berlumur debu, lengkap dengan kotoran telinga yang lupa dicuci bersih. Begitulah dunia!
Maka ketika dunia tak membagi kebahagiaan yang sama, Bukowski diam-diam masuk ke kamarnya, menenggak minumannya, sendirian, tanpa siapa-siapa, sebab di luar sana memang tak ada yang bisa dipercaya dan diajak kompromi apalagi bersolider. Ia menulis puisi, sesekali menenggak alkohol, sesekali kentut dan mengagungkan kentutnya sendiri (bacalah puisi Warm Water Bubbles yang fenomenal itu), sesekali tertawa ketika menyadari bahwa mereka yang berada di luar sana sedang berjuang untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan, sesuatu yang bisa memuaskan perutnya, sebelum jatuh dari lubang anus dengan bau busuk, lalu mengendap di tanah yang paling gelap.
Jauh sebelum realisme lusuh, Hegel, filsuf idealis asal Jerman itu mengingatkan: cara terbaik untuk menjadi bahagia adalah menerima dunia yang kita hidupi sebagai sesuatu yang niscaya. Fatalistik memang. Tetapi hiburan semacam ini cukup berguna dalam dunia yang semakin berat ini, meski harus siap menjadi bahan cercaan orang-orang yang optimis. Indonesia bukanlah tempat yang cukup strategis bagi orang-orang seperti Bukowski. Berlebihan mengonsumsi alkohol bisa menyulap wajah manusia menjadi serupa pecandu narkoba, dan itu sangat tidak menguntungkan Negara lantas harus dibasmi. Wajar saja, realisme lusuh kurang dikembangkan, sebab orang-orang takut distigma sebagai yang kehilangan harapan, pesimis, pesakitan, menodai optimisme bersama menuju Indonesia maju di tahun 2045, walaupun para pencuri uang dari golongan elit semakin gencar memotong pucuk mimpi itu.
“Sudahlah, kau tinggalkan saja realisme lusuh itu!” seorang penyair asal Tangerang mengingatkan saya pada suatu hari. Saya akui, saya terbatas. Saya tidak selihai dan segenius Bukowski dalam urusan menertawai dan mencemooh dunia ini. Gaya kontemplasi artistik seperti itu tak mudah ditaklukkan. Butuh keberanian, apalagi berbahasa di tanah air tecinta ini, tanah air yang dihuni oleh sebagian manusia yang mudah menganggap sesiapa saja yang melawan arus konvensi sebagai orang gila dan kafir. []
Penulis:
Petrus Nandi lahir di Pantar, Manggarai Timur, NTT, pada 30 Juli 1997. Ia giat menulis puisi, cerpen, dan esai. Karya-karyanya tersiar di beberapa media seperti Tempo, Suara Merdeka, Basis, Mata Puisi, Medan Pos, Lensasastra.id, dll. Buku puisinya berjudul Memoar. Saat ini menetap di Pra Novisiat Claret, Kupang.