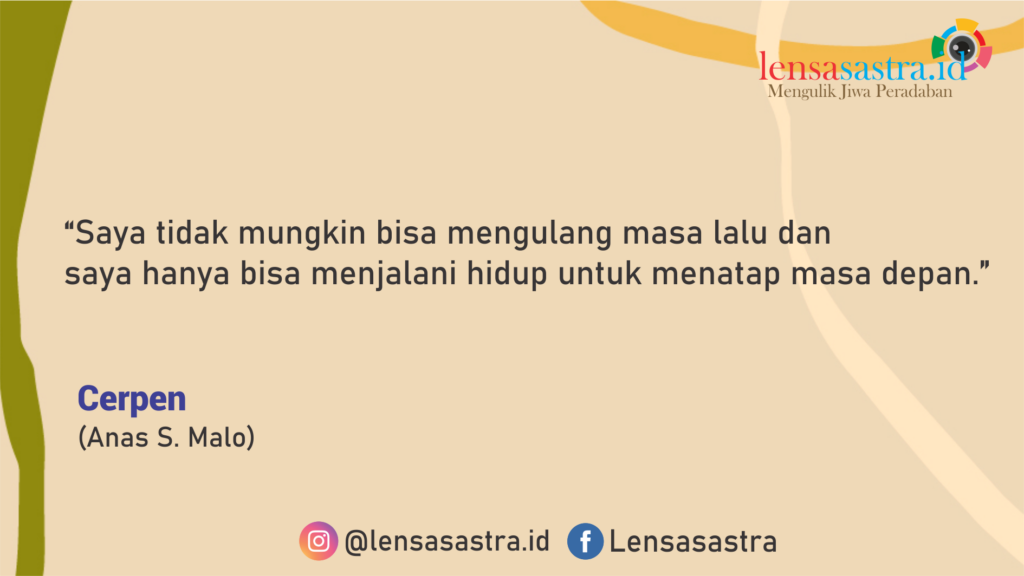
Wasiat Ibu
Ibu telah berwasiat untuk menguburkan jasadnya di belakang rumah. Dua puluh hari setelah ia berwasiat, ia mangkat dengan damai.
Di belakang rumah ada lahan kosong yang tidak begitu luas. Ditumbuhi oleh bunga-bunga rampai dan rimbun pohon beringin. Indah, sejuk. Cahaya kemilau sinar matahari membuat nisan dari batu marmer tampak bercahaya. Pohon anggur menjalar di tembok-tembok gerbang.
Dari gerbang itulah, saya menyaksikan putaran waktu tampak terhenti. Saya menyebutnya dengan gerbang waktu. Karena dari gerbang itu, saya seperti kembali ke masa-masa silam, saat ibu sering menyiram bunga-bunga rampai, memetik anggur. Atau saya merasa kembali ke masa silam ketika saya duduk di sebuah ayunan di bawah pohon rindang, pohon beringin. Pohon itu begitu kokoh penyangga ayunan. Seperti halnya ingatan saya yang tetap kokoh meskipun tertimbun oleh waktu.
Kangen membentuk bayangan ibu yang sedang menyiram bunga-bunga. Seperti beberapa tahun yang lalu, sebelum ibu serangan jantung. Sebelum nafasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat dan sebelum ia menyampaikan wasiatnya.
Ia ingin, jasadnya dikebumikan di belakang rumah. Saya pun berpikir, puluhan tahun mendatang, di belakang akan menjadi pemakaman keluarga. Selain berwasiat ingin dikebumikan di belakang rumah, ia pun juga berwasiat kepada saya untuk memberikan Mak Warsih kambing untuk dijadikan berkurban.
Sebelumnya, ibu sudah punya rencana tentang itu, namun penyakit liver yang dideritanya mendahului untuk mengeksekusi niatan itu. Namun beruntungnya, ia masih ingat dengan niatnya sebelum ia dijemput malaikat maut. Saat di rumah sakit, ibu menatap saya dengan isyarat, ia ingin membisikkan sesuatu. Dengan suara parau, ia mengucapkan kata-kata.
“Berikan Mak Warsih kambing,” pesan terakhirnya.
“Baik Bu,” ucapku menahan sesegukan. Berapa waktu kemudian, saya beserta istri dan adik saya tidak bisa menahan air mata yang jatuh, setelah ibu benar-benar meninggalkan kami.
Wak Warsih adalah pembantu setia ibu, yang merawat saya dari kecil sampai saya menikah. Untuk ukuran wanita sepuh, ia masih tampak berenergi meskipun kerut-kerut di wajahnya semakin kendur. Punggungnya pun semakin melengkung, tapi yang saya herankan, ia jarang sakit. Bahkan sejauh ini saya tidak pernah mendengar kabar bahwa Mak Warsih sakit. Bahkan, ia tidak pernah minum obat buatan pabrik.
Yang saya dengar, Wak Warsih selalu minum wedang serai kalau pagi. Ia tidak pernah memakai sandal jika ia berjalan di atas kerikil-kerikil jalanan. Barangkali itu rahasianya. Tetapi saya tidak yakin.
Tiga hari setelah kematian ibu, saya duduk di ayunan di bawah pohon beringin belakang rumah. Menatap lekat batu nisannya tertulis nama ibu dan salib. Dingin dan tenang. Kemudian saya berdiri, kemudian menyusuri bunga-bunga rampai. Saya mendengar suara burung bernyanyi seperti nyanyian gereja, sejuk sekali. Barangkali puluhan tahun yang akan datang, tanah seluas seperempat hektar ini akan menjadi makam keluarga. Ibu pasti merasa bahagia karena keluarganya berada di dekatnya.
***
Pagi-pagi sekali, pintu terketuk. Elisa sudah bangun terlebih dahulu saat adzan subuh berkumandang beberapa waktu yang lalu. Pintu itu terketuk lagi. Elisa segera bergegas menuju pintu. Ia sedikit terhenyak. Ia mendapati Mak Warsih sudah di depan pintu.
“Tumben datangnya lebih pagi daripada biasanya,” ucap Elisa.
“Kebetulan Mak lagi jalan-jalan. Mak cuma mau mengingatkan sebentar lagi sudah masuk bulan puasa. Mendiang ibu mertuamu, selalu datang ke makam kakek dan nenekmu untuk mengirim doa,” ucap Mak Warsih.
Saya sudah terbang dan menuju pintu. Setelah saya membuka pintu, Mak Warsih sudah di depan pintu dengan istri saya sedang ngobrol. Pagi itu saya belum sempat cuci muka dan gosok gigi.
“Mak Warsih ingin kita menyambangi makam ibu sebelum masuk bulan puasa. Bagaimana Mas?” Tanya Elisa.
“Apakah Mak Warsih ingin ke makam ibu juga?” Tanyaku kepada Mak Warsih.
“Tentu saja kalau diizinkan,” ucapnya.
Dulu ketika masih di kampung, saya tidak pernah menjumpai ibu ke makam kakek dan nenek saat menjelang bulan puasa. Setelah saya lulus kuliah kemudian menjadi orang urban di Jakarta, saya baru tahu jika ibu memiliki kebiasaan berziarah ke makam orang-orang terkasih. Mungkin saya sudah terlalu lama meninggalkan kampung halaman dan meninggalkan ibu dalam kesendirian, sehingga saya tidak terlalu memperhatikan perubahan yang ada pada diri ibu.
Saya dan Elisa mengajak Mak Warsih masuk ke dalam rumah untuk menyantap hidangan pagi yang sudah dimasak oleh Elisa. Mak Warsih mencuci kaki terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam.
Sembari Elisa mengambil nasi dan lauk pauk di dapur, saya bertanya kepada Mak Warsih, sejak kapan ibu suka berziarah ke makam orang-orang yang sudah meninggal.
Untuk sejenak Mak Warsih tidak langsung menjawab. Dengan senyumannya yang meneduhkan, ia bercerita soal kebiasaan ibu selama saya merantau di Jakarta.
“Ibumu sering ke makam kakek dan nenekmu bila menjelang puasa untuk mengirim doa,” yang ucapnya.
“Mak tidak tahu pasti, kapan ibumu suka berziarah, tapi yang jelas, ibumu ingin seperti kami yang sering berziarah ke makam orang-orang yang sudah mendahului kita. Kata ibumu, itu tidak bertentangan dengan agamanya, bahkan kata ibumu percaya bahwa orang-orang yang sudah meninggal, pasti mereka merasa bahagia jika ibumu menziarahi makam keluarganya,” sambung Mak Warsih.
Barangkali ibu mencontoh orang-orang di kampungnya, sebelum bulan puasa tiba, biasanya orang-orang muslim berziarah ke makam orang yang sudah meninggal dengan tujuan mengirim doa keselamatan. Dan saya sependapat dengan ibu. Siapa pun yang sudah meninggal pasti membutuhkan doa orang-orang yang masih hidup.
Ketika ibu meninggal, banyak tetangga yang melayat dan menyempatkan untuk melihat jasad ibu yang terakhir. Saat ibadah penghiburan sampai upacara pelepasan sebelum jenazah dikebumikan, para tetangga juga ikut mengiringi prosesi pemakaman, meskipun mereka hanya di halaman rumah. Bahkan, suatu ketika saat ibu tergolek di ranjang kesakitan rumah sakit, ia berwasiat agar sebelum hendak dikebumikan, Mak Warsih merias wajah ibu.
Hasilnya luar biasa, untuk seseorang yang tak pandai merias, bahkan tak pernah merias dirinya sendiri, Mak Warsih bisa merias ibu dengan luar biasa cantiknya, bahkan lebih cantik daripada wajah ibu semasa hidup. Tangan ajaib Mak Warsih bisa menyulap ibu terlihat lebih muda dan seolah-olah, ibu hanya sedang tertidur. Wajahnya terlihat berseri-seri perpaduan Tionghoa Jawa. Alisnya dibikin tebal seperti rembulan menggantung. Pipinya begitu kencang.
Selain itu, Mak Warsih juga menceritakan bahwa ibu setiap lebaran, membuat makanan yang dihidangkan untuk para tetangga yang datang ke rumah ini. Ibu merayakan lebaran seperti halnya para tetangga yang lain, meskipun tidak mengikuti ritual keagamaannya. Tapi ibu turut berbahagia saat lebaran tiba, karena saling bermaaf-maafan, saling bersilaturahmi menyambung tali persaudaraan dan saling berbagi.
Elisa membawa hidangan dari dapur. Kami pun menikmati sarapan dengan rasa syukur. Asap dari nasi yang masih panas mengepul melayang ke udara. Setelah selesai sarapan, saya mengajak Elisa dan Mak Warsih untuk berziarah ke makam ibu di belakang rumah.
Kami beranjak belakang rumah, tepatnya untuk mengunjungi makam ibu. Kami mengirim doa, tiga hari sebelum Ramadhan tiba, seperti halnya seperti adat istiadat setempat. Tentunya kami mengirimkan doa sesuai cara berdoa kami masing-masing.
Wasiat terakhir ibu yang lain adalah memberikan Mak Warsih kambing untuk berkurban sebelum kami balik ke Jakarta. Sebelum Ibu meninggal, ia menceritakan bahwa Mak Warsih hidup sebatang kara dan ia ingin kali berkurban.
Saya membeli kambing untuk Mak Warsih sehari setelah kami berziarah ke makam ibu. Setelah itu, kami berangkat ke Jakarta naik kereta api jurusan Blora-Jakarta ditemani Elisa. Saya duduk di samping jendela, melihat gunung kapur dari balik jendela. Saya tidak mungkin bisa mengulang masa lalu dan saya hanya bisa menjalani hidup untuk menatap masa depan.
Kini, ibu dan kampung halaman sudah berlalu setelah sepuluh tahun saya meninggalkan. Tetapi saya sedikit lebih lega, setelah menunaikan beberapa wasiat ibu. (*)
Penulis:
Anas S. Malo, lahir di Bojonegoro. Bergiat di Lembaga Kajian Sastra Kutub Yogyakarta dan belajar di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Sekarang ia tinggal di pesantren Baitul Kilmah, asuhan sastrawan dan Kiai Aguk Irawan. Karya-karyanya sudah tersiar di media lokal maupun nasional. Antologi cerpennya diterbitkan Belibis Pustaka berjudul Si Penembak Jitu, 2020.