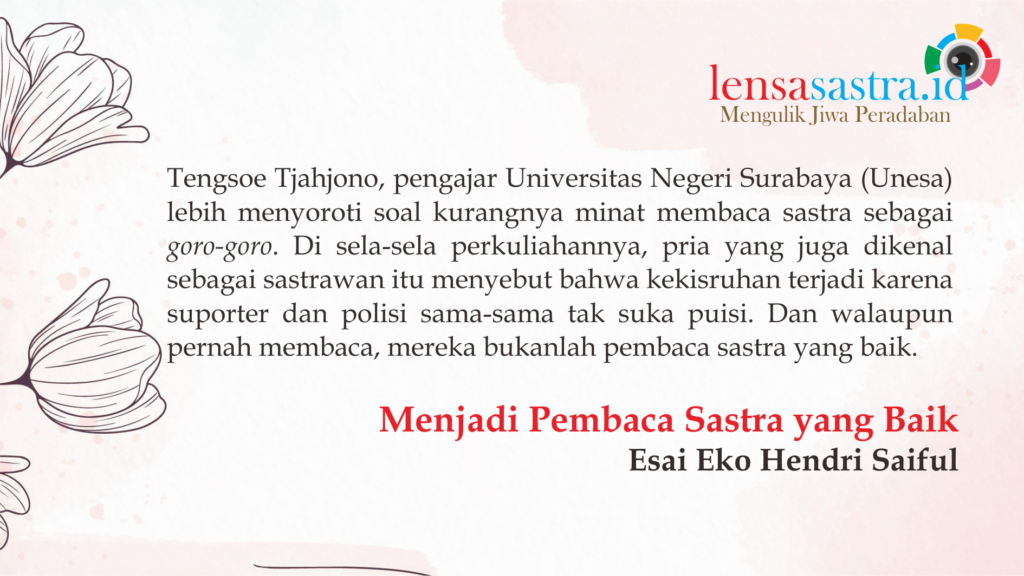
Menjadi Pembaca Sastra yang Baik
Tragedi memilukan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan memantik empati berbagai kalangan. Suporter, olahragawan, ahli hukum, psikolog, wartawan, guru, dan tenaga kesehatan turut berkomentar dengan sudut pandang dan pengalaman masing-masing. Duka itu juga mengilhami sastrawan untuk menulis karya seni sebagai wujud bela sungkawa meninggalnya Aremania.
Dan rasan-rasan terkait tragedi Kanjuruhan pun disuarakan di seluruh ruang publik. Seperti pasar, tempat ibadah, perkantoran, warung dan kampus. Yang paling banyak diperbincangkan: penyebab utama meninggalnya ratusan suporter.
Tidak menyebut soal mekanisme pengamanan. Tengsoe Tjahjono, pengajar Universitas Negeri Surabaya (Unesa) lebih menyoroti soal kurangnya minat membaca sastra sebagai goro-goro. Di sela-sela perkuliahannya, pria yang juga dikenal sebagai sastrawan itu menyebut bahwa kekisruhan terjadi karena suporter dan polisi sama-sama tak suka puisi. Dan walaupun pernah membaca, mereka bukanlah pembaca sastra yang baik.
Pembaca yang baik, dalam konteks ini, bukanlah pembaca yang jago mengeja rangkaian huruf. Pembaca yang mengerti alur cerita. Namun sama seperti pendapat Vipond dan Hunt (1984), pembaca yang baik mampu memahami nilai/ pesan dalam setiap karya sastra.
Sehingga label sebagai pembaca yang baik tak bisa disematkan secara langsung pada setiap pembaca karya sastra. Ciri khasnya pada hasrat ‘menyenangi’ yang menyertai. Keterbacaan, pengalaman, dan empati juga menjadi kunci.
Sebab membaca karya sastra sejatinya tak sama dengan membaca berita, undangan, resep obat atau pengumuman kuliah. Perlu antusiasme lebih untuk menjadi penelaah. Itu tak cukup dengan sekadar mengapresiasi unsur linguistik dalam karya seni.
Radhar Panca Dahana dalam Riwayat Negeri yang Haru: Cerpen Pilihan Kompas 1981-1990 (2019) menuliskan bahwa setiap pengarang memiliki cara unik untuk menyelipkan makna. Mungkin lewat tema, setting, alur dan dialog. Terkadang pengarang juga berupaya menyampaikan pesan lewat kekuatan tokoh seperti pada cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari.
Untuk menjadi pembaca yang baik memerlukan sejumlah hal yang perlu dipahami. Tidak saja sosial dan budaya penulisnya. Vipond dan Hunt mengingatkan soal pentingnya memahami konteks dalam membaca cerita. Konteks yang dalam versi penulis lebih mengarah pada situasi dan kondisi aktual yang terjadi.
Semisal cerpen Sepak Cinta, Gila Bola karya Eko Triono yang dimuat Jawa Pos (8/10). Karya tersebut memuat tokoh utama bernama Atika yang juga pecinta pemain dan dunia sepak bola. Cerpen muncul sebagai bentuk respon atas tragedi Kanjuruhan.
Saat ini, kemunculan karya seni terutama sastra koran memang tak lepas dari konteks sosial dan dinamika politik. Ada banyak cerpen yang muncul sebagai wujud pemberontakan pengarang terhadap lingkungannya. Ada Pula penulis yang sengaja memproduksi karya sebagai penjelmaan sikap protes terhadap kebijakan pemerintah.
Pembaca yang baik tidak saja dituntut untuk memahami penulis dan menemukan nilai dalam karya sastra. Namun juga menjadikan pesan moral tersebut sebagai pondasi perilaku. Muaranya pada peningkatan kualitas hidup yang berkemanusiaan.
Selebihnya, minat untuk menjadi pembaca yang baik tentunya tidak berhenti pada kepuasan individual. Muncul keinginan bercabang untuk mengorbitkan pembaca yang baik lainnya. Pendidikan jadi jalur efektif untuk mewujudkan misi tersebut. Itu tidak sulit.
Tidak harus diawali dengan melempar novel Saman atau Larung karya Ayu Utami pada anak. Namun cukup membacakan cerpen Kisah Pilot Bejo agar anak bisa tertawa kekel dan menyenanginya. Mungkin dengan begitu, anak akan mampu meneladani kesabaran Bejo dan tak mengulang tragedi Kanjuruhan jika kelak jadi suporter. []
Penulis:
 Eko Hendri Saiful. Mahasiswa Pasca Sarjana Unesa.
Eko Hendri Saiful. Mahasiswa Pasca Sarjana Unesa.