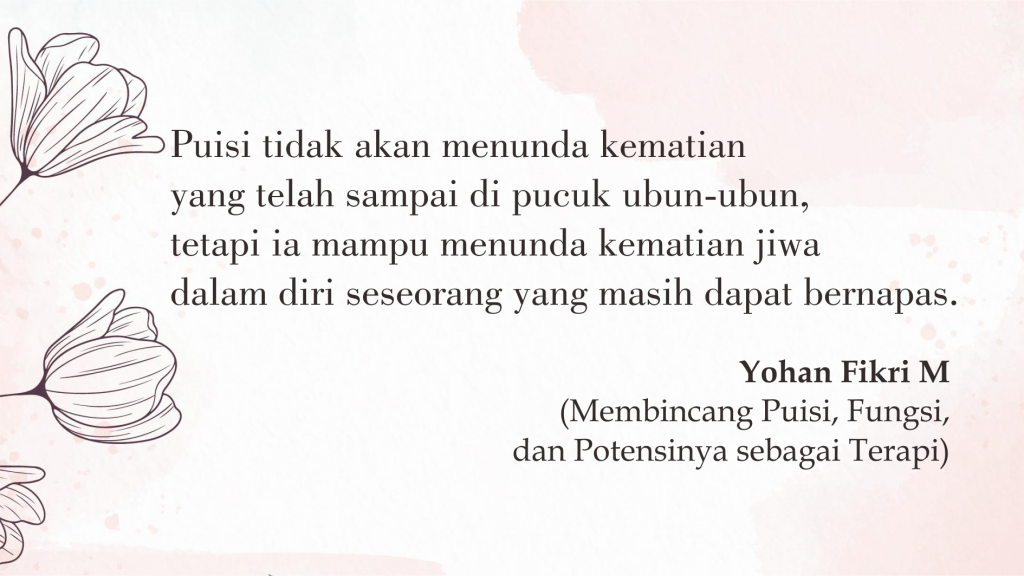
Membincang Puisi, Fungsi, dan Potensinya sebagai Terapi
Bukanlah sebuah pernyataan yang mengada-ngada sebagaimana racauan seorang hippie, apabila ada orang yang mengatakan bahwa karya sastra dapat menjadi terapi alternatif penyembuhan diri dari luka, atau mungkin juga trauma. Beban kehidupan yang kian kompleks, kecemasan akan masa depan yang kelabu, masa lalu kelam yang seakan menguntit seperti bayangan, hingga sekadar perkara patah hati akibat cinta yang berujung nahas tak jarang menjadi geronjal dalam lelampah hidup manusia. Kendati barangkali, sebuah puisi yang ditulis seseorang setelah ia ditinggal pergi oleh kekasihnya, tidak akan membuat kekasih yang amat ia cintai itu kembali ke haribaan peluknya.
Puisi mungkin tidak akan mampu menambal lambung tetangga kita yang bocor dan ususnya melilit-lilit, lantaran saban hari hanya dapat melahap sesuap nasi aking. Ia tidak akan semerta-merta menjadi mantra yang dapat membuat sembuh nasib-nasib melepuh. Toh pada kenyataannya, banyak problematika dalam kehidupan kita tidak kuasa dijangkau oleh tangan puisi, bahkan tidak bisa diselesaikan cukup dengan bermodalkan metafora paling megah sekalipun.
Tentu kita tahu, dan kita sama mengalami, pandemi Covid-19 telah berumur satu tahun lebih di negara kita, dan di usianya yang pendek itu, ia telah demikian sukses menjadi semacam mesin pencerabut nyawa. Angka kematian akibat wabah terus bertambah, dan berita perkabungan seakan-akan sedang bersaing dengan suara azan dan pepujian untuk mengkaribi mulut toa sebuah surau. Apakah kepedihan demi kepedihan itu kemudian mampu ditanggulangi oleh puisi? Tentu saja tidak.
Akan tetapi, setiap kali ada orang Indonesia yang masih menulis puisi, kita patut bersyukur. Demikian Seno Gumira Ajidarma mengatakan dalam sebuah esainya yang bertajuk “Puisi dan Kematian Budaya” (sebuah pengantar buku kumpulan puisi karya Rieke Diah Pitaloka dalam Maulana, 2012: 165-166). Sebab menurut Seno, kalau toh ia tidak berhasil menyelamatkan jiwa seseorang, setidaknya ia telah menyelamatkan jiwanya sendiri. Sebuah pernyataan yang seakan menjadi buluh damar untuk menerangi kegamangan kita sebelumnya. Sehingga kemudian, kendati pun sebuah puisi tidak menyelamatkan apa-apa—bahkan untuk sekadar cinta yang gagal, setidaknya puisi telah berhasil menjadi penawar rasa sakit yang membilur di dada pengidapnya. Puisi tidak akan menunda kematian yang telah sampai di pucuk ubun-ubun, tetapi ia mampu menunda kematian jiwa dalam diri seseorang yang masih dapat bernapas.
Di luar hal-hal di atas, jika kita mau menarik diri jauh kembali ke masa lampau, yakni pada masa tradisi lisan masyarakat Arab Jahiliyah, kita bakal tercerahkan. Bahwa puisi, rupanya tidak sekadar difungsikan sebagai wadah untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan bagi penulisnya, atau sekadar media hiburan yang dikudap sembari menyeduh secangkir teh bunga telang di beranda ketika akhir pekan tiba bagi pembacanya. Hazleton (2018) menjelaskan, bahwa puisi tidak hanya difungsikan sebagai sarana ekspresi diri. Melainkan lebih dari itu, puisi juga difungsikan oleh mereka sebagai catatan sejarah: kepedihan, keterluntaan, dan kematian selama peperangan berlangsung, misalnya, bukan tidak mungkin malah akan semakin hidup ketika digambarkan dalam bahasa puisi. Sesuatu yang barangkali tidak akan ditemukan oleh generasi jauh setelahnya, ketika mereka membaca buku-buku sejarah yang kadang kala terasa kaku dan menjemukan.
Selain sebagai catatan sejarah, dalam peperangan, oleh bangsa Arab Jahiliyah, puisi bahkan merangkap fungsi sebagai jargon pembakar semangat. Ia, layaknya kucur minyak tanah yang mampu membuat semangat redup para martir yang turun ke medan laga, kembali membara. Sehingga mereka bertambah tangguh dalam menghadapi musuh. Tidak sebatas itu, bangsa Arab Jahiliyah, yang hampir semuanya menguasai keterampilan bersyair, bahkan sampai mendudukkan puisi atau syair pada kasta yang sifatnya adikodrati. Melebihi apa yang kuasa dijangkau oleh daya nalar manusia, semisal obat bagi rasa sakit atau luka yang mereka derita pascaperang.
Dalam konteks di luar perang, beberapa puisi atau syair bangsa Arab yang populer berbentuk satire, ditulis dalam bentuk kuplet, digunakan untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang tertentu. Ini barangkali mengingatkan kita pada kisah dalam Sirah Nabawiyah, di mana Aisyah difitnah berbuat serong dengan seorang pemuda bernama Shafwan. Sebab pada peristiwa itu, mereka (bangsa Arab) secara berbondong-bondong menyindir Aisyah dengan satire yang amat tajam dan menusuk.
Merujuk dari berbagai kasus mengenai fungsi puisi di atas, ada dua hal yang setidaknya perlu kita garis bawahi, bahwa puisi—mengutip konsep Horace dalam Wellek & Warren (2016: 23), tidak hanya karya sastra yang dulce (berdaya estetis), melainkan juga utile (berdaya guna). Ia tidak hanya sekadar rangkaian kalimat indah mendayu-dayu, yang lahir dari mulut seseorang yang dimabuk kasmaran, atau ungkapan kepedihan dan keterluntaan seseorang yang tak henti didera derita sepanjang hidupnya. Kedua sifat tersebut tidak hanya melekat, tetapi juga saling mengisi. Sebagai sebuah karya seni yang bergerak di medan bahasa, dengan bahasanya yang sublim, puisi menyuguhkan ruang kontemplasi tersendiri. Sentuhan ajaib yang bisa membuat jiwa seseorang yang merasa terbuhul bisa kembali mengepak-bebas. Ia tak memberikan kepada kita kesenangan yang bersifat jasmani, melainkan sesuatu yang tak tersentuh oleh jasmani itu sendiri.
Sebagaimana Wellek & Warren (2016) juga pernah nyatakan dalam bukunya, permenungan yang disuguhkan oleh karya seni lebih dahsyat bila dibanding dengan permenungan yang dapat dilakukan sendiri oleh para penikmatnya. Kemampuan seni mengartikulasikan perenungan, demikian ucap mereka, dapat memberikan rasa kesenangan tersendiri. Sementara itu, pengalaman mengikuti artikulasi itu memberikan rasa lepas. Saya terkadang kerap membayangkan ungkapan dua pakar teori sastra tersebut sebagai pengalaman seseorang yang sedang orgasme. Sesuatu yang tak dapat diraba, tetapi ketika telah sampai di puncak kenikmatan itu, ada kepuasaan, ada kelegaan, getaran-getaran yang tak dapat ditampung oleh berbagai macam bentuk uraian.
Di samping itu, sadar maupun tidak, bahasa sebagai medan berjibaku daripada puisi itu sendiri—baik dalam wujudnya yang lisan maupun tulisan—adalah sesuatu yang begitu mudah kita produksi, kapan pun dan di mana pun itu. Yang mana dengan kemudahan tersebut, ia justru memiliki pengaruh yang amat signifikan bila sudah bersinggungan dengan mitra tuturnya. Manusia menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan, atau dogma-dogma tertentu melalui kata-kata. Maka kemudian, “Apatah merupakan sesuatu yang berlebihan? Apatah menjadi pernyataan yang mengada-mengada? Apabila puisi, sebagai sebuah karya seni, menjadi upaya tersendiri untuk menambal berbagai macam luka dalam diri?”
Jawabannya sudah tentu adalah “tidak”. Sebab semenjak jauh-jauh hari, perkembangan ilmu psikoterapi telah menyeret-serta karya sastra ke dalam ruang lingkupnya, yang kemudian jamak kita kenal sebagai bibliotherapy. Yakni memanfaatkan bahan bacaan sastra sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai problematika berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang, merawat kesehatan, hingga menanggulangi berbagai kondisi dan penyakit. Dan, bukankah hal-hal tersebut bahkan telah sejak lama diterapkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah, sebagaimana yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya? Percaya atau tidak, sejumlah pakar mengganggap bahwa puisi, sebagai salah satu genre karya sastra, mengandung potensi terapeutik tersendiri.
Satu contoh kecil, di dalam kultur pesantren, pembacaan syair-syair burdah—yang sekaligus juga merupakan ritus doa, dilaksanakan dengan harapan dan keyakinan bahwa seseorang yang sakit akan segera diberi kesembuhan oleh Yang Kuasa. Begitupun dalam kondisi musim wabah seperti saat ini. Suatu waktu, di pesantren di mana saya bermukim, pernah saya mengikuti ritual pembacaan burdah secara berjamaah bersama para santri dan kiai. Pada saat itu, saya pribadi merasa ada sebentuk kedamaian yang merasuk di kedalaman jiwa. Kata-kata (dalam hal ini yakni larik-larik syair burdah) dengan segala kemagisannya, seperti menjadi penyejuk pikiran dan perasaan, di tengah-tengah kondisi yang sedang mengalami chaos, yang carut-marut dan tanpa kepastian ini. Maka tak khayal, kalau Abdul Wachid B.S (2019) mengatakan, setiap dirinya selesai menulis sebuah sajak dan membacanya ulang, dirinya merasa yakin, sajak adalah harapan di antara tampilan citraan, dan pernyataan, yang ditegakkan untuk merobohkan keputusasaan dalam realitas kehidupan manusia. Bukankah kenyataan-kenyataan tersebut, secara tidak langsung telah menjadi argumentasi atas tesis yang menyebut, bahwa puisi memang mempunyai potensi terapeutik? Allahu a’alam. []
Gading Pesantren, 01 September 2021
Daftar Rujukan
Hazleton, Lesley. 2018. After the Prophet. Yogyakarta: IRCiSoD.
Maulana, Soni Farid. 2012. Apresiasi dan Proses Kreatif Menulis Puisi. Bandung: Nuansa Cendekia.
Wachid, Abdul. 2019. Sastra Pencerahan. Yogyakarta: Basabasi.
Wellek, Rene & Warren, Austin. 2016. Teori Kesusastraan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Penulis:
Yohan Fikri M, lahir di Ponorogo, 01 November 1998. Alumnus Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Negeri Malang. Sejumlah tulisannya tersiar di beberapa media dan antologi bersama, antara lain: Antologi Puisi Banjarbaru Rainy Day Literary Festival 2020 (2020) Perjamuan Perempuan Tanah Garam (2020), dan Yang Tersisa dari Surabaya (2020). Puisi-puisinya pernah memenangkan sejumlah perlombaan, antara lain: Juara 1 Lomba Cipta Puisi Nasional 2020 Jagat Kreasi Mahasiswa, Universitas Negeri Malang, Juara 2 Lomba Cipta Puisi Asia Tenggara, Pekan Bahasa dan Sastra 2020, Universitas Sebelas Maret, Juara 1 Lomba Menulis Puisi Majalah Komunikasi Universitas Negeri Malang, Juara Harapan 1 Festival Sastra 2021 Universitas Gajah Mada, dan Juara 1 Lomba Cipta Puisi “KOLEGA”, Himprobsi, Universitas Sebelas Maret. Bukunya yang bakal terbit bertajuk “Tanbihat Sebuah Perjalanan.” Dapat disapa melalui akun instagramnya @yohan_fvckry.