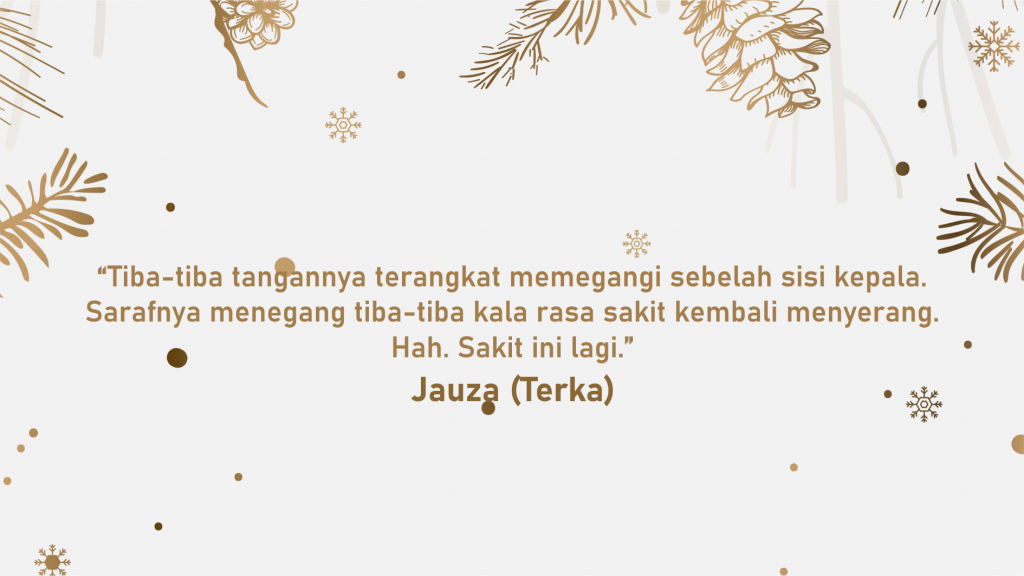
Terka
Semak sial. Rumput liar. Buruk rupa. Begitulah aku biasa dipanggil. Secara alamiah, aku tumbuh rendah di tanah. Dedaunanku menyusup liar di sela-sela tanaman hias sejenis rumput milik Nyonya Alamanda yang ditanam jarang-jarang.
Bicara tentang Nyonya, beliau tidak suka padaku. Sering kali aku dilirik dengan tatapan hinaan berbalut kebencian. Menurut beliau, aku telah merusak estetika taman minimalis impian yang ingin ia wujudkan. Aku yang merasa bersalah tidak bisa melawan ketika ia menginjak geram sembari mengancam akan mencabutku hingga ke akar-akar.
Setiap hari ketika terbangun, doa pertamaku adalah supaya Nyonya Alamanda berhenti menyiksa. Doa keduaku adalah agar aku diberi kesempatan mengetahui nama asliku. Kuharap Tuhan mengabulkan itu.
Suatu sore yang demikian mendung, Nyonya Alamanda pulang dengan wajah murung. Ia kelihatan lelah. Air mukanya masam. Kasihan. Oh, ya. Sebelum kembali bercerita, biar kuberitahu satu rahasia. Meski oleh para tanaman ia dipanggil nyonya, usia beliau sebenarnya belum terlalu tua.
“Sialan!” Seperti biasa—dengan wajah berkerut—Nyonya mendengus sambil menendang batu. Batu berukuran sedang itu melayang beberapa hasta dan langsung terpantul ketika membentur salah satu sisi dinding. Aku cemas sekali. Kuharap batu itu tidak terbang mengenai wajah Nyonya yang cantik seperti bunga hias. Untungnya tidak.
“Kerja dari pagi, dituntut ini-itu, kenyang menelan hinaan dan aku masih enggak dihargai!” rutuk Nyonya Alamanda.
“Berhenti saja, Nyonya,” bisikku gugup. “Itu akan lebih baik untuk kesejahteraan hidupmu.”
Seakan mendengar sahutanku, Nyonya Alamanda berbalik dan mendelik. Aku gelagapan, buru-buru mengalihkan tatapan.
“Sejak kapan sih rumput liar itu tumbuh di sana? Kalau saja enggak ada si jelek itu, tamanku pasti enggak semak dan akan terlihat indah sekali. Sepulang kerja aku bisa bernapas lega menatap keindahan taman dan enggak bakalan stres seperti ini! Mau dicabut, lama, enggak ada waktu. Pakai cangkul, makin capek dan bisa kena tanaman di sebelahnya. Nyuruh tukang kebun, harus keluar biaya lagi. Hah! Kenapa sih hidupku seperti ini?”
Kuberanikan diri menoleh lagi. Nyonya yang tadi sibuk mengeluh kini mencengkeram kepala sambil mengujar a-a-a-a-a dengan penuh histeria. Terlihat putus asa.
“Maaf.” Mataku berkaca-kaca. Aku mencoba menguatkan diri. Sudut mataku menangkap mawar berduri yang sedang menertawai. Kenapa, ya, aku tidak diciptakan secantik dia? Aku juga ingin tahu rasanya jadi tumbuhan yang diinginkan dan diperjuangkan oleh majikan.
***
Dari gosip para tumbuhan, aku mendengar kabar bahwa Nyonya Alamanda jatuh sakit. Aku langsung tahu kalau kabar ini benar ketika Ibunda Nyonya Alamanda—Bu Wahyu—tiba sambil memasang raut wajah panik.
Langkah perempuan yang berusia senja itu melangkah tergesa—memangkas jarak dari halaman kecil tempat para tumbuhan tinggal—menuju pintu rumah bercat putih pucat.
Pintu dibuka perlahan oleh seseorang di baliknya. Bu Wahyu masuk sambil memapah Nyonya Alamanda yang lemas sehingga kesulitan berjalan.
“Sudah ibu bilang, kan? Kalau saja kamu menikah, mungkin enggak akan repot begini. Atau, kenapa enggak pulang aja? Ibu bisa jaga kamu di sana.”
“Kenapa sih harus bahas pernikahan?” terdengar teriakan frustasi dari dalam rumah. Itu suara Nyonya Alamanda, sepertinya menyeruak keluar melalui kisi-kisi jendela.
Kami semua tersentak. Terkejut.
Mendapat asupan drama, pohon mangga di depan jendela terkikik bahagia. Pohon itu bilang kalau Nyonya Alamanda dan Bu Wahyu sedang berdebat di ruang tengah. Menurut kabar dari Pohon Mangga, ada ketegangan di antara Nyonya dan ibunya. Para tanaman—termasuk aku—menajamkan telinga.
“Supaya ada yang menjaga kalau kamu sakit begini.” Suara Bu Wahyu terdengar setelah beberapa waktu senyap.
Aku curiga. Pembicaraan ini mungkin ada hubungannya dengan omongan tetangga yang heran kenapa Nyonya belum menikah di akhir usia dua puluhan, padahal teman-teman beliau sudah merencanakan pernikahan sejak menyusun skripsi perkuliahan, entah itu karena ingin melarikan diri dari kepenatan atau pun karena sudah bertemu jodoh betulan.
Beberapa malam lalu, aku juga mendengar Nyonya berbicara ketus di telepon. Ada sesuatu tentang ia tidak ingin pulang kampung lagi karena bosan mengalami invasi privasi. Sepertinya hal itu membuat ia kesal setengah mati.
“Aku enggak butuh dijaga, Bu. Aku bisa jaga diri sendiri.”
“Kalau gitu, gimana kamu bisa sakit begini coba?”
“Karena capek!”
“Kenapa enggak berhenti kerja?”
“Kalau berhenti kerja, terus aku dapat uang dari mana? Rumah ini juga, walau kecil, aku beli dengan uang tabungan hasil bertahun-tahun kerja. Bahkan, masih ada cicilan yang tersisa! Aku enggak mau berhenti, pulang dan jadi gulma enggak berguna! Lebih daripada itu, aku enggak mau pulang dan direcoki dengan pertanyaan kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah? Memang kalau aku menikah, hidup mereka bakalan berubah?”
Sunyi sesaat. Aku berdebar, cemas. Seketika perkataan Nyonya menjadi samar. Tapi, satu yang kudengar jelas: gulma.
Gulma. Nyonya juga pernah memanggilku seperti itu. Jadi ia benci padaku karena tidak ingin menjadi gulma? Kenapa? Karena gulma jelek dan tidak berguna? Seperti aku?
Bu Wahyu menarik napas panjang. Ia tidak ingin ini berakhir menjadi perdebatan, seperti yang selalu terjadi selama ini. Maka, perempuan itu menyerah. “Sudah minum obat?” Nada suaranya melunak.
“Belum.”
“Kita ke rumah sakit sekarang. Siap-siap.”
“Bu, sakitku bukan sakit yang harus diobati ke rumah sakit. Aku cuma lelah. Butuh istirahat dan sesekali menghirup udara segar di taman yang cantik.”
“Taman?” Bu Wahyu mengernyit. “Bagaimana dengan taman di halaman?”
“Itu enggak pantas disebut taman! Enggak terurus.”
“Kalau mau, Ibu bisa bantu kamu mengurusi taman.”
“Oh? Boleh! Ada rumput liar jelek di antara tanaman hias yang cantik. Itu mengganggu sekali. Tumbuh banyak seenak jidat. Kalau Ibu enggak capek, bisa tolong bantu cabut nanti? Manda mau rebahan sebentar lagi.”
Aku gemetar mendengar keputusan Nyonya yang mengerikan. Apa aku harus merelakan nyawaku segera? Jika memang itu untuk kebaikan Nyonya, aku rela. Tapi, Tuhan … tidak bersediakah Engkau mengabulkan terlebih dahulu doa sederhanaku?
***
Sudah beberapa menit Bu Wahyu mengamatiku lamat-lamat, tanpa suara. Sepasang mata miliknya nyaris memicing. Dahi perempuan itu berkerut. Apa ia rabun? Kalau benar, kuharap angka rabun matanya cukup tinggi sampai-sampai ia akan salah mengira aku sebagai mawar. Dengan begitu, mungkin saja aku akan selamat.
“Krokot hijau?” Bu Wahyu bergumam sambil mengelus dagu. “Iya. Ini kan krokot yang sering dipakai Simbok dulu.”
Ha? Krokot? Itu kan … bahasa Inggris kecoak. Aku sering mencuri dengar pembicaraan sekumpulan anak sekolah dasar yang lewat di depan rumah Nyonya Alamanda sambil menghafal kosa kata. Sepertinya cukup mirip.
Kubalas tatapan Bu Wahyu dengan keprihatinan. Pasti rabunnya terlampau parah sampai ia mengira aku seekor kecoak.
“Permisi, ya.” Bu Wahyu berjongkok. Wajahnya mendekat. Perlahan, Bu Wahyu mencabut lembut beberapa helai daunku. “Daunmu akan digunakan untuk obat.”
Obat? Oh. Jadi aku ini tanaman obat? Setelah agak lama terkesiap tak percaya menerima kebenaran yang selama ini tidak diketahui, ada rasa bangga yang menyusup masuk ke dalam hatiku. Aku tersenyum malu. Jadi, selama ini aku ternyata berharga? Kalau tahu begitu….
Diam-diam aku melirik Mawar, berencana sedikit menyombongkan diri. Tapi, bunga cantik itu tidak peduli. Ia sedang sibuk berdansa bersama angin.
Ah, sudahlah. Yang penting sekarang aku sangat bahagia. Tuhan mengabulkan doaku. Bukan hanya satu, tapi keduanya!
***
“Udah mendingan?”
“Iya. Badan terasa segar dan sakit kepala hilang. Walau rasanya agak aneh, sih.”
“Lha iya. Namanya aja jamu. Kamu kan enggak suka jamu, makanya terasa aneh.”
“Memang bahan dasarnya apa, Bu?”
“Krokot hijau dan campuran beberapa rempah.”
“Krokot hijau? Apa tuh?”
“Itu, yang daunnya bisa dimakan sebagai lalapan juga. Kamu mau? Sekalian Ibu masak makan siang.”
“Oh, masak untuk Ibu aja.”
“Kenapa?”
“Aku harus masuk kerja siang ini. Barusan dikabari.”
“Tapi, kamu masih sakit.”
“Enggak apa-apa, Bu. Oh, ya. Nanti aku telepon tukang kebun yang direkomendasikan temanku barusan. Ibu enggak usah lagi mengurus taman. Pulang aja, pasti banyak urusan yang harus Ibu selesaikan. Tukangnya datang agak sorean.”
“Tapi ….”
“Soalnya,” Alamanda menyela, “sepetak taman di depan sana harus benar-benar ditata. Enggak apa-apa walau keluar biaya. Yang penting harus cantik. Menyegarkan mata, menyegarkan hati. Kata teman Manda, hal ini krusial sekali untuk kesehatan jiwa.”
“Oke, tapi ….”
“Manda buru-buru, jadi udah dulu ya, Bu.”
“Iya, tapi krokotnya jangan dicabut semua! Rapikan saja. Itu sudah langka.”
Alamanda tidak mendengar dengan saksama. Dengan hati riang ia masuk kamar untuk memilih baju di dalam lemari. Sudah lama ia tidak merasa sesegar ini. Dengan tubuh dan pikiran yang dijalari energi positif, ia percaya diri bisa menaklukkan hari.
***
Petang menjelang. Dengan wajah kusut masai, Alamanda pulang. Dari lampu beranda yang masih mati, ia tahu Ibu sudah pergi. Dikuasai lelah, ia ingin menumpahkan cercaan terkait pekerjaan, namun urung ketika melihat kejutan yang menanti.
Oh. Belum selesai seratus persen, tapi tukang kebun itu sudah melakukan tugasnya dengan baik. Senyuman sarat kepuasan terbingkai manis di bibir Alamanda.
Kerisauan gadis itu sedikit mereda kala melihat taman yang sudah apik tertata di bawah terpaan satu lampu taman bercahaya hangat keemasan. Di ujung sana, ada ceruk kecil yang sepertinya akan dijadikan kolam. Pada sisi kolam yang belum terisi, sepasang bangau buatan berwarna merah muda berdiri dengan anggunnya.
Nah, ini yang ia butuhkan. Alamanda tersenyum puas. Mungkin ia akan memesan satu bangku taman dan semua akan sempurna. Rumah ini akan benar-benar menjadi suaka. Tak hanya bebas dari omongan tetangga nun jauh di sana, ia juga bisa menjernihkan pikiran di taman indah yang baik untuk kesehatan jiwa.
Tapi, tunggu, kenapa rasanya ada yang kurang? Apa ia harus mengganti pot gerabah dengan pot berwarna putih cerah?
Hm ….
Alamanda menggelengkan kepala, berusaha mengalihkan pikiran dan kembali berjalan. Tiba-tiba tangannya terangkat memegangi sebelah sisi kepala. Sarafnya menegang tiba-tiba kala rasa sakit kembali menyerang. Hah. Sakit ini lagi. Tapi, tidak masalah! Nanti ia akan menelepon sang ibu untuk menanyakan perihal jamu menyegarkan tadi pagi.
“Di mana, ya, Ibu beli bahan-bahannya?” Alamanda meringis.[]
22 Agustus 2020
Penulis:
Jauza. Penulis adalah lulusan Sastra Inggris. Beberapa cerita pendek dan puisinya dimuat di media cetak lokal seperti Harian Analisa dan Harian Waspada, juga antologi bersama. Pernah memenangkan beberapa lomba menulis.