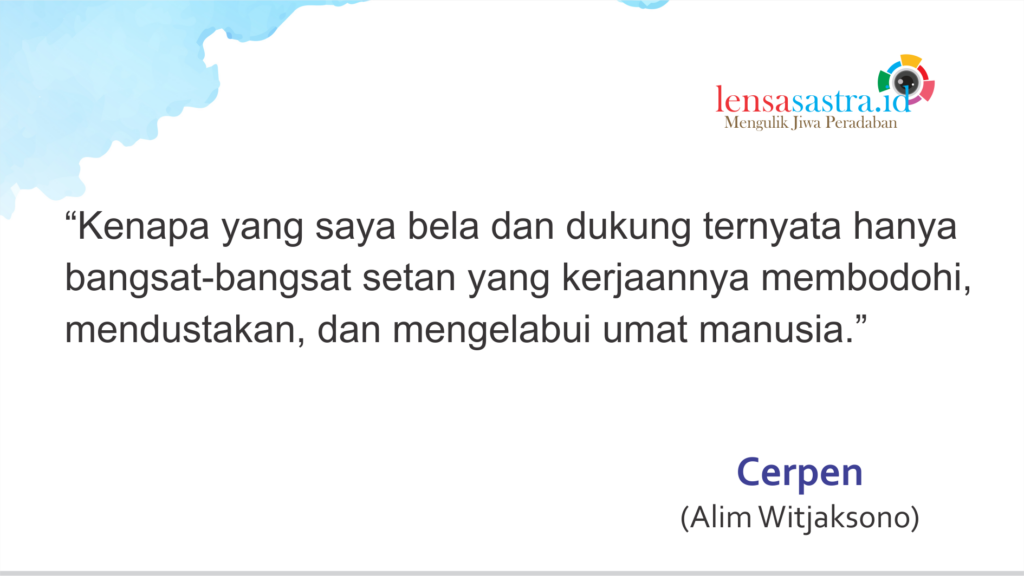
Nurdin Sambo
NAMA saya Nurdin Sambo. Siapa pula yang tidak mengenal saya. Semua orang tahu bahwa saya ini tak lain dan tak bukan adalah patriot, pejuang dan pembela negeri dan tanah air ini. Buku-buku sejarah perlu mencatat itu. Mengapa tidak? Dulu, di zaman Pak Harto, ketika upacara akan dimulai pada Pk. 09.00, sejak Pk. 08.00 saya sudah berada di lapangan.
Tentu saja saya merasa senang jika Sekjen Partai Kantosa (Karya Sentosa) melihat keberadaan saya yang sudah datang sebelum yang lainnya. Lalu, bagaimana jika Pak Sekjen tidak melihat? Biarlah, tidak apa-apa, karena bagaimanapun saya ini adalah militan sejati, dan saya sepakat dengan pernyataan banyak pengamat melalui siaran televisi, bahwa upacara pengibaran bendera merah-putih pada hari kemerdekaan RI, adalah peristiwa bersejarah yang tak boleh dilupakan oleh siapa pun.
Sekali lagi saya nyatakan bahwa saya adalah Nurdin Sambo, dan jangan macam-macam dengan saya. Sebab, saya sudah mengabdikan diri menjadi pembela Orde Baru selama bertahun-tahun. Boleh dibilang, saya termasuk ujung-tombak garda depan bagi keamanan dan ketertiban nasional negeri ini. Selama puluhan tahun saya memimpin Gerakan Pemuda Orde Baru (GPOB), tak ada yang berani macam-macam dengan GPOB. Tak ada lagi Gerakan Pengacau Keamanan, tak ada lagi Organisasi Tanpa Bentuk, tak ada lagi ekstrim tengah, karena semuanya itu telah kami tumpaskan sampai ke akar-akarnya.
Itulah yang tadi saya katakan bahwa saya ini pantas tercatat sebagai patriot dan pahlawan sejati negeri ini. Lain kali akan saya perhitungkan anggaran khusus, untuk mengamplopi oknum-oknum wartawan, baik luring maupun daring, agar senantiasa tak bosan-bosan menampilkan statemen politik maupun pembangunan yang saya lontarkan di hadapan mereka.
Saat ini memang jarang media-media nasional maupun lokal yang mau “bekerjasama” dengan orang-orang seperti kami, tetapi itu hanyalah idealisme dari insitusi jurnalistik dan kewartawanan. Adapun mengenai orang-orang yang masih bisa diajak berunding secara personal, saya masih kenal beberapa namanya.
Untuk itu, saya menghimbau presiden terpilih sekarang dan seterusnya, agar mengikuti jejak-langkah demokrasi yang pernah dicanangkan oleh Bapak Presiden Orde Baru selaku pemimpin tunggal saat itu. Banyak yang mengira beliau sudah mati padahal beliau masih “hidup” saat ini. Saya harap presiden sekarang, juga punya jasa dalam menata ulang demokrasi agar kembali ke khittah semula yang dicanangkan Orde Baru
Di tengah upacara bendera pada tahun lalu, saya menyuruh semua anggota GPOB mengenakan pakaian loreng tentara tapi disertai warna kuning. Saat itu, Sekjen Partai Kantosa melakukan inspeksi dan berjumpa dengan saya, lalu sengaja saya mengelap ingus yang keluar dari hidung dengan saputangan berwarna sesuai yang ia kehendaki. Supaya dia melihat dan menyadari bahwa semua unsur yang melekat pada diri saya identik dengan warna kesukaannya. Bahkan, saya pun melengkapi motor gede yang saya miliki dengan berhiaskan pita-pita dan bendera-bendera sesuai warna yang ia sukai
Mengenai soal ingus? Entah mengapa, sejak masa pandemi Covid 19, saya sering terserang flu dan pilek, dan ingus seringkali keluar dari hidung saya yang sudah di atas 60-an ini. Tapi itu soal lain, meskipun saya berharap agar presiden terbaru lebih mengutamakan orang-orang seperti kami yang layak mendapatkan vaksinasi Covid terlebih dahulu. Tetapi, apakah presiden mementingkan warna lain selain warna yang kami sukai? Sepertinya tidak juga. Ia memilih orang-orang yang melayani masyarakat serta bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tetapi, bukankah orang-orang seperti kami inilah yang ada di baris depan dalam melayani masyarakat? Bukankah saya ini seorang patriot dan pancasilais sejati? Plis dong ah!
Sekali lagi saya tegaskan, saya adalah Nurdin Sambo. Secara pribadi, sebenarnya saya lebih suka warna hijau ketimbang kuning yang identik dengan daun-daun beringin yang akan gugur. Tetapi, hijau mencerminkan warna hutan dan pepohonan rindang. Hijau bagaikan warna rerumputan yang subur. Di sisi lain, ada bagusnya juga warna merah yang menyala bagaikan bunga-bunga mawar yang bermekaran di penghujung musim hujan.
Dengan penuh kerendahan hati, saya sebagai pejuang militan Orde Baru, sebenarnya saya juga seorang religius dan berpegang-teguh pada nilai-nilai agama. Di negeri ini, banyak orang percaya pada takhayul seperti kekuatan benda-benda pusaka atau arwah-arwah leluhur. Banyak juga orang percaya adanya kekuatan mistis seperti teluh dan santet. Untuk melindungi diri dari kekuatan jahat itu, kita memerlukan penangkal dan jimat-jimat. Kini, sebagai seorang anggota partai, ketergantungan saya sudah beralih pada simbol-simbol partai untuk melindungi diri. Di atas baju loreng kuning, saya pasang lencana yang menggambarkan sebuah pohon rindang. Dengan pelindung itu, saya percaya, setan manapun tidak akan berani menggoda dan mengganggu saya. Jiwa saya benar-benar suci dan bersih, serta layak dinobatkan sebagai pahlawan dan pelindung rakyat serta pembela tanah air.
Sebagai pengagum ajaran militerisme Orde Baru, saya tekankan bagi para anggota agar tak perlu mempelajari pemikiran Mark atau Angel (saya tidak tahu apakah tulisan ini benar atau salah). Saya sendiri tidak tertarik membaca bukunya. Sebab, kedua orang itu banyak mengilhami gerakan makar yang menimbulkan adanya peristiwa G30S/PKI. Cukup bagi para anggota GPOB mendengarkan nasihat dan petuah yang disampaikan Presiden Soeharto, pemimpin besar Orde Baru, baik melalui siaran televisi maupun radio. Terutama, setelah adanya pengambilalihan kantor telekomunikasi yang berada di depan kantor Kostrad (Komando Strategi Angkatan Darat) semasa tahun 1965-an.
Saya paham betul semboyan-semboyan yang tertulis di dinding-dinding kota seperti, “NKRI Harga Mati”, “Jagalah Persatuan dan Kesatuan Nasional”, “Ganyang Komunis” dan sebagainya. Atas nama khittah Orde Baru, saya sepakat dengan pernyataan bahwa sensor adalah bagian penting dari perjuangan nasional. Untuk itu, hal terpenting bukanlah keseluruhan dari jalannya suatu cerita, akan tetapi penggal sajalah satu bagian dari cerita, atau potonglah satu frase yang siap pakai pada momen yang tepat untuk membungkam lawan-lawan politik. Misalnya, jika kita ingin menyudutkan seorang pejabat sekelas menteri sekalipun, tunjuk saja batang hidungnya, lalu katakan dengan tegas: “Pak Menteri, kata-kata Anda itu seperti orang komunis!” Nah, dengan begitu saya bisa menjamin, dia bakal takut dan gemetaran membayangkan tentara atau intelijen negara yang siap melempar mereka ke lubang-lubang sumur.
Sekali lagi, saya adalah Nurdin Sambo. Saya sudah hafal betul dengan doktrin-dokterin semacam itu. Apa boleh buat, tiga huruf “PKI” tetap saya pertahankan sebagai dagangan politik saya dan kader-kader saya. Saya sudah paham tuduhan para mahasiswa dan generasi milenial, bahwa orang-orang seperti kami tak lebih dari birokrat-birokrat borjuis. Hahaha, semula saya mengira bahwa tuduhan semacam itu baik-baik saja. Kami merasa perlu seperti mereka yang ingin hidup tenteram dan sejahtera.
Para penyiar dan presenter televisi pada acara infotainment kadang menyebut istilah itu sebagai orang berduit, elit politik atau selebritas sosialita yang selalu mengendarai mobil mewah, punya villa di Puncak, Anyer atau Bali, menyimpan banyak uang di bank dan seterusnya dan sebagainya. Saya paham betul figur-figur semacam Aiman Witjaksono, Rosiana, Hafis Azhari hingga Najwa Shihab, dan saya kenal betul karya-karya tulis mereka yang nyeleneh dan tak tahu diri. Apa yang mereka tulis dalam buku Pikiran Orang Indonesia itu? Data-data dari mana mereka mendapatkan itu?
Memang seumumnya, para menteri, anggota DPR dan pimpinan partai politik, selalu punya mobil mewah dan rumah gedongan. Istri dan anak-anak mereka hidup tenteram dan sejahtera. Sebagian dari anak-anak mereka sekolah di luar negeri. Mereka seakan tak tahu menahu, perihal saudara-kerabat dan sepupu mereka sedang terpanggang matahari saat menunggu bus atau angkot di trotoar jalan. Sementara mereka yang hidup glamor, dengan bangganya mengenakan kemeja, dasi dan sepatu jetset, sedangkan kaum wanitanya mengenakan tas dan pakaian serba impor, karena apa-apa yang terbuat dari dalam negeri terkesan murah dan kampungan belaka. Jadi, saya kira memang semua elit politik Orde Baru adalah kaum birokrat borjuis, dan wajar saja jika saya dan anak-istri meniru dan meneladani jejak-langkah dan gaya hidup mereka.
Tidak berselang lama, para mahasiswa dan budayawan menjelaskan bahwa istilah “birokrat borjuis” tak lain dari sifat tak terpuji, laiknyaya perbuatan para koruptor yang dilindungi pemerintah Orde Baru. Di sisi lain, ada pengamat sosial yang menyatakan bahwa istilah GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) adalah istilah yang dipakai Orde Baru, yang merupakan jiplakan belaka dari Gerakan Pengaco Keamanan yang pernah dipakai penjajah Belanda hingga KNIL, di mana Pak Harto pernah menjadi salah seorang anggotanya.
Dari waktu ke waktu, semua istilah, jargon dan semboyan yang saya pelajari menjadi semacam traffic jam yang berdesakan macet di otak kepala saya. Hal itu membuat kepala saya pusing dan kliyengan karena harus berkejaran dengan istilah-istilah baru yang dipakai generasi milenial secara berhamburan.
***
Saya terkejut ketika presiden sekarang–setelah beberapa kali ganti presiden– menunjuk menteri pertahanan negara dari kalangan sipil di partai lain, dan bukan seorang militan Orde Baru dari Partai Kantosa seperti saya. Saya kecewa sekali. Sebenarnya, mereka wajib mendengar petuah saya ini. Kadang-kadang saya berpikir, mengapa presiden memilih para menterinya secara tidak jelas. Mereka bahkan bukan tergolong patriot sejati seperti saya.
Ada sinyalemen yang menyatakan bahwa mereka yang dipilih itu lebih berpandangan luas dan lebih merakyat. Lalu, kurang merakyatnya apa saya ini? Kurang luas seberapa wawasan dan pandangan saya ini? Sudah bertahun-tahun mengabdi dengan amat setia di bawah panji-panji Orde Baru, lalu yang dipilih menjadi menteri justru orang sipil biasa yang kurang dikenal di mata saya? Walah welah, barangkali pintu gerbang kiamat akan segera ambrol dan ambyar!
Padahal, saya sudah membuktikan ketulusan hati saya berikut para anggota GPOB yang saya kerahkan untuk selalu datang satu jam lebih awal. Setiap kali diadakan upacara bendera, terutama pada tanggal 17 Agustus setiap tahun, apa yang kurang pada pengabdian saya?
Baiklah, saya mau bercerita perihal upacara bendera ini. Karena bagaimanapun, pada momen ini bukan saja orang nomor satu di negeri ini yang akan tampil selaku inspektur upacara, melainkan juga dihadiri oleh mantan menteri dan presiden sejak Pak Harto tidak lagi berkuasa. Pernah seorang mantan presiden ikut menghadiri upacara. Dulu saya sangat bersimpati kepadanya. Tetapi, setelah ia mengeluarkan statemen tentang pentingnya pemikiran Karel Mark (entah benar atau salah tulisan nama ini) agar dipelajari angkatan muda sebagai ilmu pengetahuan yang berharga, kontan saya tidak lagi menghargai bahkan membenci tokoh satu itu.
Pada upacara kali ini, banyak kalangan seniman, budayawan, ekonom, akademisi dan pemikir sekelas doktor dan profesor. Biarkan saja, saya tak perlu menghakimi mereka satu persatu. Sebab, untuk menjadi patriot bangsa yang sejati, saya perlu melewati jalan berliku dan harus menyarungkan kepartaian saya terlebih dahulu. Beberapa profesor yang kepalanya botak barangkali akan gosong terbakar matahari tropis di bawah tenda yang disediakan khusus untuk para undangan dari kalangan teratas.
Sementara itu, waktu sudah menunjukkan pukul 09.30. Upacara seharusnya dimulai sejak Pk. 09.00 tepat. Para undangan wanita yang kebanyakan mengenakan kebaya, mulai kegerahan lalu berkipas-kipas dengan kipas lipat yang dibawa di tas-tas mereka. Kalangan intelektual, akademisi dan para profesor ingin sekali berkipas-kipas, tapi barangkali merasa khawatir martabat mereka sebagai elit negara anjlok, mereka memilih tenang berdiri. Mereka membiarkan dirinya terpanggang matahari katulistiwa, dengan peluh bercucuran di balik jas-jas tebal mereka. Sementara itu, saya mencoba menyempil di bawah tenda tamu undangan, seolah-olah sedang merapikan barisan agar duduk dengan teratur di belakang kursi para elit politik. Pokoknya, saya berupaya keras membuat diri saya kelihatan berguna di mata mereka.
Pukul 09.45, mobil Sekjen Partai Kantosa telah datang, diikuti oleh beberapa motor gede. Percayalah, saya adalah orang pertama yang bertepuk tangan, agar diikuti oleh tepuk tangan para anggota GPOB lainnya. Saya berinisiatif menjadi orang pertama yang mendekati mobilnya. Berkat pengalaman sebagai penjaga keamanan, pengetahuan saya cukup khatam dalam soal menjaga ketertiban nasional. Dengan sigap, saya membukakan pintu mobil. Beberapa wartawan mengambil foto kami berkali-kali karena mengira saya sebagai tokoh terpandang juga.
Saat itu, saya bisa dengan mudah menyalami tangan sang Sekjen, persis pada saat para wartawan memotret kami. Karena itu percayalah, saya Nurdin Sambo, sebagai militan Orde Baru yang rendah hati, tidak melakukan ini untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kemaslahatan dan keamanan umat dan bangsa ini.
Sirene menyala. Presiden sudah terlihat. Aba-aba dimulai. Semua bersiap dan bertepuk tangan ketika Presiden menuju tempat duduknya. Sebagai militan yang bermartabat dan kompeten, saya berdiri di dekat podium upacara. Panitia upacara sebenarnya hendak memberikan tugas ini kepada tentara atau anggota intel, tapi akhirnya saya bisa meyakinkan mereka agar memberikan tugas ini kepada GPOB. Saya bisa meyakinkan mereka dengan mudah, karena mereka orang-orang yang paham pekerjaan, secara turun temurun, dan sudah dianggap ahlul bait.
Pada mulanya mereka agak ragu, tapi setelah saya selipkan amplop yang agak tebal akhirnya mereka mau juga. Tapi awas, Anda jangan menuduh bahwa ini suap, pelican maupun gratifikasi, namun lumrah saja sebagai tanda dan ucapan terimakasih karena sudah memberikan waktunya bercakap-cakap dengan saya. Dalam hal ini, saya sudah merasa kenyang mendengar kabar bahwa di negeri yang pancasilais dan taat beragama ini, entah kenapa orang-orang akan lebih rajin bekerja jika saja ada sedikit pelican. Eit maaf, maksud saya, “ucapan terimakasih”.
Soal mengurus mikrofon dan peralatan di sekitar podium itu amat penting bagi saya. Dengan itu, kita bisa mendahului pembicara dari pihak manapun. Kita bisa maju ke atas mimbar, menaik-turunkan mikrofon, dan kalau perlu mengetesnya berkali-kali. Coba bayangkan, di depan Anda akan ada Presiden Republik Indonesia. Bukan suatu yang mustahil jika kita bisa berfoto bareng dengannya. Boleh jadi kita juga akan mendapat perhatian khusus dari sang presiden. Maaf, ini bukan sikap oportunis, tetapi lumrah saja, sebagai pengabdian untuk kepentingan negara pada momentum yang sangat menentukan dalam perjalanan sejarah bangsa.
Selanjutnya, sirine kembali berbunyi. Motor-motor kumbang masuk lapangan upacara. Begitu juga dengan serombongan tantara bersenjata lengkap. Dari depan, samping dan belakang. Sebab, siapa tahu akan ada penyusup atau teroris yang bisa datang kapan saja. Seperti suatu hari, saat seorang jenderal berkunjung ke suatu tempat di daerah Banten. Baru saja ia keluar dari mobilnya, tahu-tahu seorang penyusup masuk entah dari mana, lalu menikam jenderal itu dengan sebilah belati yang kemudian segera dilarikan ke rumah sakit. Hal ini, boleh jadi akan terulang kembali serta menimpa siapapun, termasuk diri saya sebagai patriot dan militan Orde Baru.
***
“Sst! Presiden datang, Presiden sudah datang!”
Saya berdiri di dekat mikrofon. Tegak seperti pohon beringin terjemur matahari. Dada saya membusung, siap menyambut Presiden turun dari mobilnya. Bagi saya, abad milenial ini sungguh miliknya. Negara kepulauan yang besar ini tentu dipimpin oleh pemimpin besar. Barangkali dia satrio piningit atau semacam Ratu Adil, atau bahkan manusia setengah dewa. Bagaimanapun, negara bangsa identik dengan presidennya. Kita tak bisa menampik dari fenomena itu. Jika membahas soal Prancis tentu identik dengan nama Napolen, Uni Soviet tentu identik dengan Lenin, Cina tentu saja Mao. Begitu juga, tak mungkin kita bicara Indonesia tanpa menyebut bapak bangsanya Jenderal Soeharto, eit maaf, maksud saya Bung Karno.
Kini, Presiden RI tepat berada di depan saya, lengkap dengan daging dan tulangnya. Saya pernah menatap poster raksasa yang memampang sosoknya sedang berjalan di tengah pasukan tentara yang hormat kepadanya. Sementara itu, matanya jauh menatap tajam ke depan, mengarah ke bintang merah di cakrawala. Ia seakan siap membawa rakyat menuju gerbang masa depan yang gemilang. Oh, air mata haru, penuh emosi, dan air mata patriotisme meleleh di pipi saya. Presiden berjalan diiringi gemuruh tepuk tangan dan himne penyambutan. Ia menuju kursi sandar merah, kemudian duduk dengan tegap, dan upacara siap dimulai tepat Pk. 10.00 siang.
Ketika Presiden menyampaikan pidato kenegaraan, tak begitu banyak yang saya simak, kecuali saya lebih memperhatikan logat Jawanya. Pembicara lainnya memiliki logat yang berbeda-beda. Ada yang dari Medan, Banten, Makassar, Irian Jaya, Aceh dan seterusnya. Padahal dulu, sewaktu Pak Harto memimpin RI, kebanyakan elit politik berasal dari etnis yang sama dengan sang presiden. Tetapi sekarang, zaman sudah lain. Dan presiden baru tentu tak mau mengambil tindakan sebodoh itu.
Seusai upacara, saya pun mendekati kalangan budayawan, ulama, jurnalis senior, serta beberapa pakar politik terkemuka. Tetapi anehnya, mereka kurang menaruh hormat kepada saya sebagai patriot dan militan Orde Baru. Ah, biar sajalah, barangkali mereka cemburu dan irihati pada saya. Sebenarnya, saya tahu penyebabnya, mengapa para budayawan itu tidak menyukai saya yang sangat mencintai bangsa ini. Suatu ketika, saat kementerian pendidikan dan kebudayaan mengadakan lomba baca puisi beberapa waktu lalu, saya terlibat aktif menulis bait-bait puisi yang kemudian saya bacakan di hadapan para seniman nasional. Mereka sepertinya terdiam, terbungkam, atau barangkali kagum terpukau pada gubahan puisi yang saya buat dan saya bacakan dengan lantang di depan panggung Taman Ismail Marzuki, Jakarta:
Oo betapa sangat menyedihkan
Melihat jenderal-jenderal itu mati
Dan dibuang di lubang buaya
Hidup Pak Harto,
Yang amat sangat berjasa dan sentosa
Mengangkat mayat-mayat jenderal
Bersama pihak Amerika yang membantu kami
Memberitakan peristiwa itu ke seluruh dunia
Ya, kami dari Gerakan Pemuda Orde Baru
Siap mendukung pemimpin negara
Yang kembali pada khittah Pak Harto
Sebagai bapak pembangunan
Terutama pembangunan ekonomi berkelanjutan….
Bagaimana? Hebat kan puisi yang saya tulis itu? Sebelum saya menulis puisi itu selama berminggu-minggu, sebenarnya saya belajar banyak dari karya-karya seniman senior, terutama yang menyuarakan pesan-pesan Orde Baru. Dan bila Anda melihat penampilan saya di panggung, maka Anda pun akan terpukau berat, dan boleh jadi akan menyejajarkan saya dengan penyair kondang WS Rendra, Chairil Anwar, maupun Taufik Ismail. Lebih dari mereka malah.
Tapi sayangnya, para budayawan yang menjadi juri bersikap tak acuh pada penampilan saya. Puisi-puisi saya yang membela Pak Harto dianggap puisi anak TK. Karenanya, saya tak terlampau kaget ketika mereka enggan menyunggingkan senyumnya untuk saya, pada saat upacara 17 Agustus itu.
Di sisi lain, di zaman Orde Baru dulu, saya memang pernah mengapresiasi Pak Harto yang melakukan pembredelan suratkabar, serta memberangus beberapa budayawan yang tidak memihak dirinya. Buku-buku yang mengkritik dan mempersoalkan kezaliman penguasa Orde Baru lebih baik disingkirkan dan dimusnahkan saja. Meskipun saya pusing juga ketika ada seorang sastrawan bernama Pramoedya Ananta Toer, yang berkali-kali masuk jajaran nominasi untuk penghargaan nobel sastra. Sastrawan itu pernah juga menulis di buku 100 Tahun Bung Karno (Liber Amicorum) dengan judul sepanjang kereta api: “Semua Lawan Bung Karno Sekarang Terseret ke Meja Mahkamah Sejarah”.
***
Munculnya generasi milenial yang mampu bergerak tanpa batas, membuat kepala saya kliyengan tujuh keliling. Kami harus berhati-hati akan munculnya pihak-pihak yang memanfaatkan GPOB dan orang-orang seperti kami. Kekhawatiran saya beralasan saat melihat penayangan film dokumenter hasil garapan sineas Amerika, berjudul “The Act of Killing”.
Oleh karena itu, saya Nurdin Sambo, sebagai militan Orde Baru segera menugaskan orang-orang GPOB untuk mengawasi pembuatan film tersebut. Dan saya pun – tentu saja – merasa bangga ketika diminta Joshua Oppenheimer (sang sutradara) untuk terlibat aktif selama proses pembuatan film tersebut. Selain kemahiran saya mengurusi mikrofon di podium, saya juga mahir untuk berakting dalam film yang kemudian dikenal dunia dan publik Indonesia, setelah masuk dalam jajaran nominasi Oscar sebagai film dokumenter terbaik pada 2012 lalu.
Tiba-tiba muncul beberapa jurnalis dan sastrawan, menulis artikel di LENSA SASTRA, serta menilainya sebagai cakrawala baru untuk membongkar kezaliman penguasa Orde Baru selama 32 tahun berkuasa. Ada apa ini? Ada soal apa ini? Bukankah saya hanya diminta sang sutradara untuk tampil sebagai salah seorang aktor, karena memang saya dikenal sebagai militan Orde Baru selama puluhan tahun ini?
Saya pun mengerahkan banyak anggota GPOB agar tampil selaku figuran dalam film tersebut. Dan saya merasa bangga dengan itu, seraya menunjukkan pada sang sineas Amerika, bahwa anak-anak buah saya juga layak dianugerahi penghargaan sebagai aktor-aktor terbaik. Tetapi, apa yang terjadi kemudian? Apakah sutradara Amerika itu ingin membohongi saya dan GPOB, sebagai militan-militan Orde Baru, yang memihak seorang pembunuh dan penjagal yang terlibat menghabisi orang-orang tak berdosa, tanpa proses pengadilan sejak tahun 1965 lalu?
Apa yang dia maksud? Kenapa kepala saya kliyengan terus-menerus? Kembali saya putar ulang film “The Act of Killing” tersebut. Tetapi, setelah saya renungkan baik-baik… ya ampun! Saya tak sanggup… saya tak kuat menontonnya kembali!
Film itu benar-benar menampilkan diri saya sebagai tokoh yang memihak penjagal dan pembunuh! Tidaaak! Ampuuun! Apakah selama ini saya tidak menggunakan nalar dan akal sehat sebagai manusia waras? Di mana hati nurani saya? Kenapa selama puluhan tahun ini, saya bersikap seperti orang sableng dan senewen di dalam rumah sakit jiwa…?
Tak berapa lama, muncul lagi angkatan muda milenial yang membangun komunitas pecinta novel Pikiran Orang Indonesia, ditambah lagi kasus Bjorka yang dibentuk beberapa gelintir orang Indonesia yang direkrut oleh Silicon Valley di California. Ada apa ini? Kenapa segala perubahan ini membuat kepala saya tambah pusing tujuh keliling? Tentu mereka juga punya kemampuan membongkar pembicaraan saya dengan para pengusaha yang mewarisi kekayaan militerisme Orde Baru, pada tanggal sekian, hari apa, menit dan detik ke berapa, bahkan bertempat di mana. Saat ini, mereka sudah mulai berulah membongkar rekam-jejak (footprints) beberapa jenderal yang terlibat dalam peristiwa Mei 1998 hingga pembunuhan aktivis HAM Munir. Adduh biyuuung!
Lalu, siapa sebenarnya yang saya bela dan lindungi selama ini? Apakah saya membela negara dan bangsa ini? Kenapa pikiran saya seakan klop dengan frekuensi iblis yang kerjaannya menakut-nakuti orang lain? Kenapa yang saya bela dan dukung ternyata hanya bangsat-bangsat setan yang kerjaannya membodohi, mendustakan, dan mengelabui umat manusia, khususnya terhadap bangsa dan negeri tercinta ini?(*)
Penulis:
Alim Witjaksono adalah pengamat dan peneliti sastra mutakhir Indonesia, juga pegiat hak-hak asasi manusia (HAM) Indonesia.